- “Menulis,” kata Plato, “menumpulkan ingatan karena bersandar pada apa yang tertulis, menjadikan usaha mengingat tidak lagi dari dalam diri, melainkan dari marka luar.” Tidak kurang dari filsuf klasik sekaligus pegulat ini untuk menggugat budaya tulis menulis.
- Membaca, sebagai kegiatan pasca-menulis, hanya satu dari sekian cara untuk mengunduh informasi. Jika nasehat kepada penulis adalah untuk membaca, tidak lain karena dua hal belaka: melihat konvensi kebahasaan dan keaksaraan tertulis, serta mengunduh informasi. Jika yang pertama memang mau tidak mau harus dilakukan sebagai misi pengarsipan, yang kedua sendiri mengalami invaliditas karena informasi tidak melulu tercetak.
- Membaca, seagung apa pun tampaknya saat ini, pernah mengalami peyorasi. Ketika mesin cetak mulai jamak digunakan dan kertas sebagai bahan baku semakin murah, dengung kepanikan moral atas maniak membaca pernah berdenging di kepala-kepala manusia abad ke-18.
- Maka, membaca sebagai aktivitas dalam peradaban, adalah biasa belaka. Dalam masyarakat yang terkomodifikasi, membaca malah merupakan kegiatan konsumsi biasa belaka.
- Pengarsipan barangkali adalah kemajuan paling manusiawi, dan kehilangan arsip adalah tragedi. Terbakarnya perpustakaan dalam peristiwa penaklukan dan geliat penerjemahan serta pemustakaan menjadi penanda naik turunnya zaman. Pertanyaan tetap harus diajukan: bagaimana pengarsipan seharusnya dilakukan? Apakah melulu melalui pena dan kertas?
- Zaman telah bergerak sedemikian untuk ‘melampaui’ membaca: adanya arsip audio-visual mengizinkan transformasi dan transmisi pengetahuan yang lebih inklusif.
- Jika dalam perkara membaca karena meromantisasi aksara, bolehlah. Aksara toh merupakan pencapaian akbar peradaban manusia setelah roda, tuas, dan roti. Namun, meletakkan aksara sebagai supremasi adalah keputusan buruk belaka. Zaman berkembang mengakomodir segala bentuk manusia, termasuk mereka yang mengalami kesulitan menatah informasi lewat aksara. Menyupremasikan aksara semata karena status quo merupakan bentuk kemunduran, dan ironi belaka.
- Jikalah kegiatan membaca dimasukkan sebagai kegiatan kebudayaan, maka membaca pun seharusnya tidak terhindarkan dari kritik. Hal ini tidak lagi membicarakan soal resensi; melainkan membaca itu sendiri. Membaca sebagai proses sosialisasi dan penyerapan informasi tidak berhenti di tataran ‘tinggal-membaca-saja’. Membaca, dianjurkan mempunyai penilaian pula, sebagaimana memasak — maka ada kaidah, atau dengan benar.
- Resensi diplomatis adalah racun bagi khazanah kritik. Resensi diplomatis adalah sebuah kepengecutan tanpa justifikasi yang cukup, alih-alih berani. Terlepas dari riwayat membaca yang sudah menggunung atau baru membukit, menjatuhkan penghakiman terhadap bacaan adalah sah-sah saja. Penegakan selera, dalam ranah kritik, bukanlah gatekeep — jika intensi gatekeep sendiri adalah mengucilkan, maka resensi yang keras justru memberikan tiket masuk ke lebih banyak pihak, setidaknya dalam gelanggang kritik.
- Benar bahwa tiap orang berhak menulis apa yang mereka alami dan ketahui, namun mengandalkan apa yang mereka alami dan ketahui belaka melahirkan buku-buku otobiografis yang membosankan, seperti kata Kazuo Ishiguro. Otobiografi pada akhirnya meletakkan orang-orang pada keterlemparan untuk menjadi megalomania, narsisis, dan cekak karena sarat pembelaan diri.
- Tidak semua pembaca yang menang kuantitatif adalah pembaca yang baik. Pembaca yang menghabiskan 100 buku roman remaja tidak lebih baik dari pembaca yang menghabiskan 25 buku tentang sesuatu yang diminatinya. ‘Baik’ di sini, dalam nalar jenis informasi apa yang diserap dan kualitas informasinya.
- Tidak semua buku adalah buku yang baik untuk dibaca. Contoh mudahnya: Mein Kampf karya Adolf Hitler, hoax The Protocols of the Elders of Zion, buku-buku conspiracy theorist, dan sebagian besar buku ‘pengembangan-diri’ yang tidak lain merupakan teks yang ditulis di antara sinisme masam, faux-stoicism, dan apa yang kusebut sebagai, self-imposing alienation.
- Menjadi pembaca haruslah kritis, tidak perlu diutarakan pun kudunya begitu. Karena tidak semua buku yang dibaca pada akhirnya selalu bacaan bagus. Menganggap setiap bacaan adalah baik merupakan sikap denial. Sebagai pembaca tekun, tersandung bacaan buruk adalah wajar belaka.
- Membaca tidak menjadikan pembaca sebagai makhluk superior. Hal ini tidak dilepaskan dari masalah struktural dan akses, baik dalam artian sempit di mana buku tidak merata sebarannya, atau dalam artian yang lebih luas, di mana buku sebagai medium tidak melulu inklusif.
- Harus ada upaya untuk meruntuhkan membaca sebagai kegiatan agung dan menjadikannya lazim, hal ini tidak lepas dari masalah struktural mengenai ketersediaan literasi. Sehingga kita bergerak dari ‘membaca-tidak membaca’, menjadi ‘membaca buku bagus-membaca buku jelek’.
- Jika susunan kimiawi di otak dan kebiasaan serta akses mengizinkan, maka kegiatan membaca seharusnya lazim dilakukan, atau malah kewajiban. Sebagaimana adagium, “with great power comes great responsibility.”
- Jangan menolak kenyataan bahwa membaca adalah konsumsi, dan pembaca adalah konsumen. Sebagai konsumen kritis, perlu rasanya untuk menyadari bahwa buku jelek akan selalu ada dan selera akan berubah seiring riwayat.
- Membacalah dari rasa ingin tahu, dan kalau bisa, sinisme. Sinisme mensyaratkan pelakunya untuk tidak sok tahu.
- Urusan bagaimana mengukur baik-buruk bagus-jeleknya adalah perbincangan panjang lain lagi. Semoga ada waktu untuk ditulis.
Mengenai Membaca

Discover more from Kasat Kata Kultur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

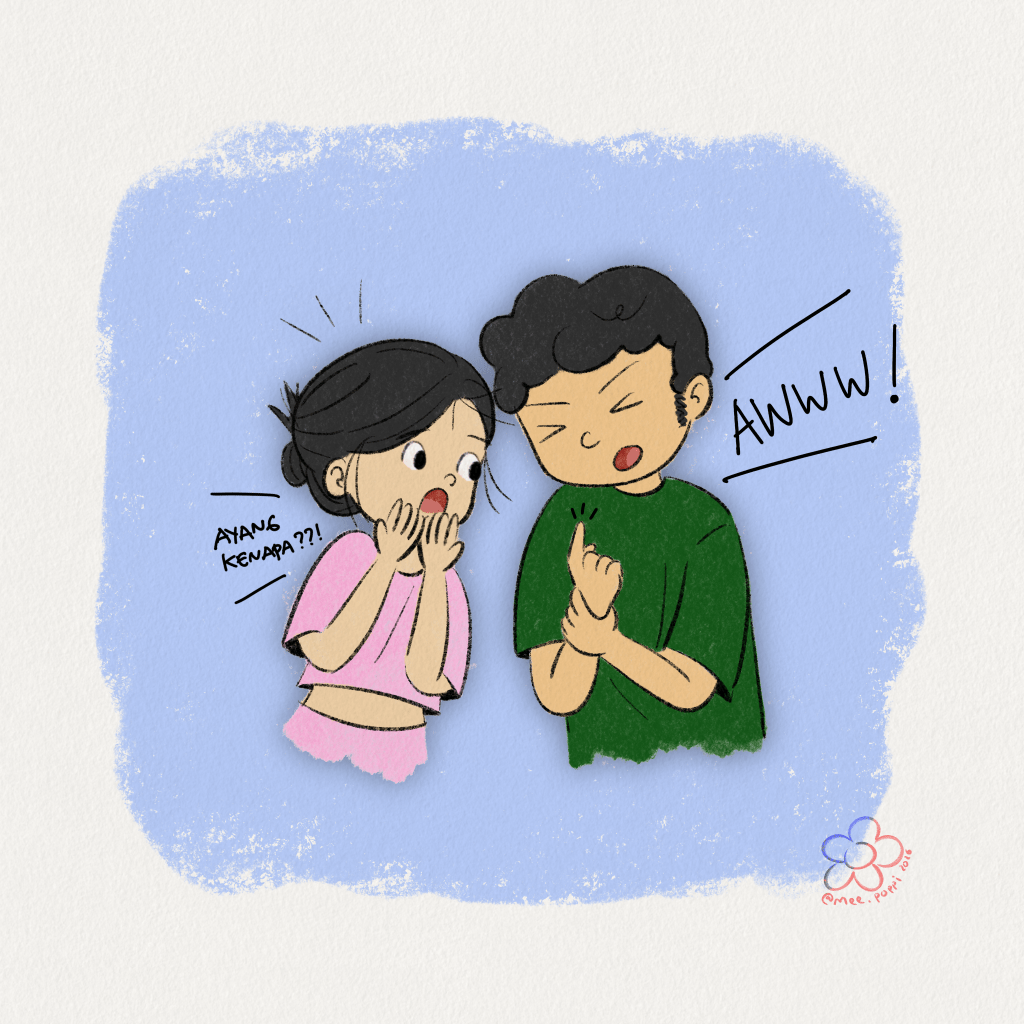


Leave a comment