Bagian Pertama. Keterasingan dan Inefisiensi.
Jika tugas insinyur adalah mengefisienkan kerja, birokrat memang bertugas memperpanjang dan memperumitnya. Bila tugas insinyur adalah memangkas waktu, tugas birokrat adalah memangkas umur dengan panjangnya urusan yang menuakan. Insinyur menuntaskan masalah, birokrat menumpuknya dengan berlaku tele-tele.
Kebertele-telean dari pada birokrat ini ternyata universal. Tabiatnya yang nyaris kebenaran fisika ini tidak terhindarkan. Penyakit birokrasi ini menjangkit hanya karena disebar oleh satu-satunya makhluk yang punya ide cemerlang tersebut. Seperti sawan, penyakit birokrasi pula merubuhkan jiwa-jiwa si makhluk. Birokrasi menelantarkan kemanusiaan untuk hal-hal yang sifatnya prosedural dan teknis belaka.
Mulanya penyakit ini mudah ditelusuri muasalnya: manusia berbiak berganda dan harus ada yang mengatur itu semua. Seiring dengan kembangnya nalar, kaum sedikit yang mencengkeram leher orang banyak sebagai upaya untuk mengatur peradaban dipandang tidak lagi manusiawi. Diciptakanlah demokrasi, dan dari usaha-usaha pengaturan, temuan berwujud birokrasi ini dicuri dari feodalisme karena efisiensinya. Ironis, zaman membuktikannya terbalik. Birokrasi menjadi sinonim belaka dengan inefisiensi. Mengapa?
Dugaan bisa ditarik dari usaha dan maksud dari birokrasi itu sendiri. Birokrasi mengangankan bahwa urusan-urusan manusia bisa dipangkas, diarsipkan, digariskan, didelegasikan sebagaimana roti atau perabotan dibikin. Birokrasi diandaikan menjadi mesin bantu untuk menuntaskan urusan banyak orang sekaligus. Sayangnya, kelemahan mesin tersebut rupanya adalah tiap baut dan murnya sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah manusia.
Manusia, apalagi jika dihadapkan dengan manusia lain, punya lapisan-lapisan serba rumit yang tidak mampu diuraikan; karena toh, lapisan ini tidak bisa dinalar sebagaimana insinyur menalar masalah. Lapisan-lapisan ini bahkan enggan diletakkan dalam kategorisasi ‘masalah’ dan ‘solusi’ belaka. Lapisan ini semakin kusut karena pada birokrasi tersemat kuasa, dan pada tiap-tiap manusia yang menjadi mur dan baut birokrasi tampaknya dibuat mabuk pula oleh semata sematan. Urusan menjadi berlarut-larut karena remehnya hasrat berkelindan dengan makna kuasa serta lubang-lubang kelemahan ‘mekanis’ yang sengaja dibiarkan ada dalam ‘mesin’ birokrasi.
Korban dari evolusi birokrasi ini tidak lain adalah orang-orang yang berurusan dengannya, yang tidak pungkir adalah orang-orang kebanyakan. Birokrasi yang dimaksud sebagai daya dukung peradaban, menjadi adibangsat besar yang harus dihadapi. Inilah yang kemudian menjadi konflik K., tokoh kita dalam The Trial dan The Castle karya Franz Kafka.
Penjabaran K. dalam kedua novel tersebut buat saya menggambarkan begitulah sensasi terjebak dalam pusaran birokrasi: klaustrofobik, menggelisahkan, dan dingin. Kesumpekan ini tampak dari bunga-bunga bahasa milik para birokrat. Selimur bahasa ini masih pula ditamengi oleh lapisan-lapisan struktural yang malah menjauhkan K. dari tujuannya. Absurditas para pamong ini melarutkan K. dalam kegelisahan tak berkesudahan dan meracuni kesehariannya. Tidak ada yang akbar dari kegelisahan hidup K., semua begitu biasa, namun membuat K. begitu nirdaya. K. sebagai manusia tidak pernah terealisasi karena disibukkan oleh perkara (yang di)panjang(-panjangkan) dan (di)rumit(-rumitkan). Hingga akhir, K. entah tidak mencapai tujuannya atau malah berakhir tragis. K. terasingkan oleh inefisiensi dan hiruk-pikuk administrasi. Kafka melalui K. gamblang ingin menelanjangi kegelisahannya atas realitas absurd dari birokrasi ini. Kafka ingin membisikkan ke telinga para pembaca: birokrasilah pangkal masalahnya.
Toh, jika mengimajinasikan birokrasi sebagai masalah yang dihadapi insinyur, birokrasi yang efisien sebagai solusi hanya akan mendehumanisasi birokrat dan warganya; seperti yang telah diramal oleh Weber. Pun, ramalan itu juga sudah mewujud di sekeliling kita.
Bagian Kedua. Keterasingan dan Kesendirian.
Namun dalam kelindan baku emosi dengan birokrasi, K. masih sempat-sempatnya menjadi casanova. Subplot romansa ini bukan tanpa sebab. Ruang aman yang diberikan oleh kekasih-kekasih K. membumikan keresahan K., menjadikannya merasa manusia lagi. Laiknya mercusuar, sering konflik-konflik asmara yang dialami oleh K. menjadi penerang bagi setiap carut marut di kepala K.. Asmara menjadi pengingat, bahwa relasi-relasi romantik yang manusiawi ini pun, menjadi penting untuk kemudian dicerabut begitu saja ke dalam sesaknya mata topan birokrasi. Setiap kali K. diambil dari kekasihnya, semakin ia diingatkan betapa raksasa mapan berjubah administrasi membuatnya merasa begitu kerdil dan sendirian.
Keterasingan yang menyudutkan tidak hanya muncul dalam kisah-kisah K.. Kafka menelanjangi dirinya dalam surat otobiografis yang dialamatkan kepada ayahnya. Dari sinilah terbaca muasal segala kegelisahan Kafka yang tertuang pada tiap tulisannya. Berbinar barangkali mata Freud membaca bukti otentik tesis-tesisnya lewat surat-surat Kafka. The Judgement kemudian, menjadi alegori romantis yang sarat pula dengan kesendirian, atau keterputusan antara jiwa tokoh/penulis dengan orang lain. Inilah keterasingan tingkat selanjutnya dari karya-karya Kafka; tidak hanya disebabkan suprastruktur administrasi, melainkan juga prakondisi psyche yang mendorongnya semakin jauh ke dalam jurang yang menggemakan gelisahnya, tanpa ada yang benar-benar menyahut.
Bagian Ketiga. Keterasingan dan Jerih Usaha.
Kita semua tahu kisah tentang seorang buruh yang terbangun menjadi serangga. Metamorphosis kemudian menjadi isyarat, betapa fantastisnya pergulatan eksistensial seorang pekerja sejak ia membuka mata. Namun lebih dari itu, kisah ini menawarkan hal-hal yang tidak kalah fantastis dalam pembacaan yang lebih dalam. Samsa, si buruh-menjadi-serangga, hanya mengkhawatirkan soal pertemuan dengan kliennya ketika ia berubah menjadi serangga! Samsa, dalam kebingungannya, memutuskan untuk meresahkan hal yang bukan menjadi highlight dari kejadian luar biasa yang menimpanya. Dia memutuskan untuk meresahkan hal-hal yang sudah dikerjakannya bertahun-tahun, dengan meletakkan harapan agar bisa terus melakukannya untuk bertahun-tahun kemudian! Sungguh absurd. Namun, jika kita lebih jeli melihat sekeliling, tidak terhindarkan dekat dengan kita. Coba lihat rekan kerjamu: berapa banyak yang didera oleh sakit kepala dan asam lambung naik ke tenggorokan namun masih memutuskan untuk berangkat bekerja?
Konflik keinginan Samsa, yang karena kondisinya menjadi mustahil tercapai, menjadi apa yang menggerakkan cerita dan sekitarnya. Keresahan ini mimesis belaka, bahkan untuk hampir seratus tahun kemudian. Buruh dalam tingkat apa pun rela menyambut kematian itu sendiri jika diperlukan agar ada yang bisa dimakan di hari esok. Jerih upaya yang berulang-ulang, dari hari ke hari, menjadi lakon default dari buruh-buruh sehingga tidak sempat untuk berhenti dan bertanya, “mengapa?” Keterasingan sebab jerih ini laku lucu nan tragis belaka. Anekdot ini muncul pula dalam An Imperial Message, di mana sang pembawa pesan harus terjebak dalam lautan manusia untuk menyampaikan pesan yang tidak akan pernah sampai. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada…privilese. Tugas adalah tugas, berulang dan berulang. Itu-itu saja.
Dan jika kita berani balik kanan, tak pelak kita masuk ke mulut si kucing di jalan buntu, sebagaimana nasib si tikus di A Little Fable.
Bagian Keempat. Kafkaesque Adalah Anekdot Sysiphian Belaka.
Kemudian, karena laku-laku mekanis kita, kita pun dihukum. Semakin efisien dan cerlang, kita dihukum dengan jerih yang lebih banyak. Semakin melambat dan belok dari tata aturan, maka dosa kita terajah di atas tubuh sampai mati. Pun begitu, tidak ada yang ingin membereskan pangkal masalahnya. Tidak ada yang ingin mulai untuk mengganti mur dan baut yang berkarat. Tidak ada transendensi dalam repetisi karena semua yang usang tidak kunjung dibuang. Begitulah, nasib kita seperti terdakwa di In The Penal Colony. Dunia tidak pernah mengizinkan penghakiman yang adil karena semua orang sibuk dengan cara-cara mapan yang terpatri di atas batu, demi ‘agenda besar’ yang ditulis di perkamen tua tanpa ada pengajuan keberatan.
Tugas-tugas kemudian menyemat menjadi identitas. Aku adalah tugas-tugasku, sehingga kemudian abai dengan aku-yang-mengada-di-dunia. Poseidon merupakan anekdot Kafka lainnya, tenggelam dalam tugas-tugasnya hingga lupa akan dunia dan kodratnya. Dewata, karena suprastruktur yang bongkah, menjadi profan belaka. Tidak ada transendensi, hanya ego karena dirinya menolak menjadi bagian dari liyan. Sehingga konsekuensinya, menolak pula menjadi Dasein yang larut dalam pemaknaan yang produktif.
Begitulah, membaca Kafka adalah membaca perenungan maha panjang dan kontinyu soal absurditas dan keseharian. Repetisi tugas yang berulang-ulang, dalam suprastruktur mahabengis yang tak acuh, mewatak dalam penalaran manusianya yang terjebak antara memberi makan egonya atau memberi makna eksistensinya. Pilihan yang tampaknya mudah, rupanya sulit diputuskan karena konsekuensi berada-dalam-dunia. Seperti si tokoh dalam A Hunger Artist yang mati kelaparan bukan karena berpuasa lama menjadi kemampuan supranaturalnya, melainkan hanya karena tak ada pangan yang cocok di lidahnya. Kita menjebak diri kita dalam, “tirani tanpa tiran,” kata Arendt. Kita mengkalibrasi jiwa kita dalam governmentality, mentalitas untuk mengatur barisannya sendiri hanya karena ingin berada-dalam-dunia. Suprastruktur — dan birokrasi sebagai infrastrukturnya menyebabkan kita menyerahkan jiwa kita pada relasi pengawasan panoptikon. Sadar meletakkan diri kita dalam pembongkarpasangan oleh mata mesin yang maha melihat. Menjadikan kita menolak merenungkan keberadaan-kita-dalam-dunia, setidaknya seperti anjing dalam Investigations of A Dog. Menolak menimbang liyan, la visage d’Autrui — kata Levinas, sebagai penalaran etis dan jalan keluar dari komedi putar keterasingan.


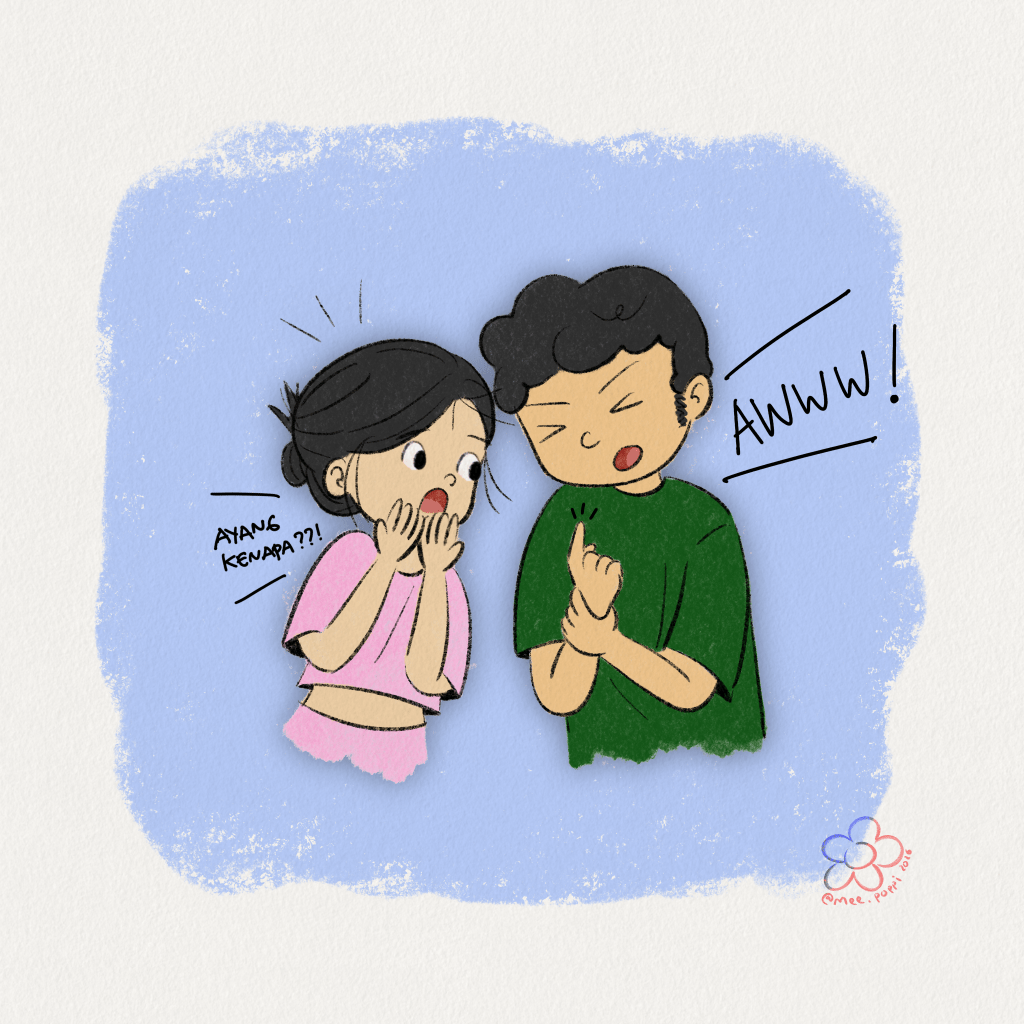


Leave a comment