Aku sedang berjalan pulang saat gemuruh dan gluduk menyapa langit-langit kotaku. Hari gelap seharian, aku sudah was-was bakal kehujanan selepas jam kerja. Memikirkan kemeja dan sepatu basah sudah bikin semangat agak berantakan. Dan aku menolak semangatku diruntuhkan air yang tumpah dari langit. Maka, aku mulai bergegas.
Benar saja, hujan memutuskan terjun bebas tidak berapa lama. Aku memutuskan untuk berteduh di minimarket. Untung belum ada yang basah. Hujan semakin rapat, seperti tirai abu-abu. Angin turut menghantam, dibawanya air langit ke mana-mana. Aku terjebak.
Saat itulah, dari teras minimarket, aku melihatnya. Sosok yang tampak mendekat dari arah badai. Suara kecipak langkahnya tertutup hujan yang derasnya seperti meriam air. Dia tiba di teras itu, menyunggingkan senyum ke arahku, lalu turut menunggu. Aku mengedarkan pandangan, menyelidikinya dari atas ke bawah. Aneh, untuk seseorang yang baru saja menembus badai, pakaiannya terbilang kering. Seakan yang dilaluinya hanya gerimis. Oh, dia menawan juga.
Dia memergokiku sedang memandangnya, lalu senyum merekah di wajahnya. “Deras ya, Mas,” ujarnya. Wajahku merona, “iya, Mbak.” Aku tidak berani memulai obrolan lebih jauh. Perasaan aneh — bukan canggung — masih menggantung di setengah sadarku.
Dan hari-hari berikutnya berjalan persis seperti putaran jam. Hujan mengguyur sepulang kerja tepat di dekat minimarket itu. Dan dia selalu datang saat hujan begitu rapat. Sosoknya yang samar di derasnya air mulai kukenali. Langkahnya selalu sama, bunyi kecipaknya selalu seragam. Dan anehnya, selalu saja dia tampak seperti kena gerimis alih-alih badai.
Hari kesekian belas, aku memutuskan untuk membuka obrolan, “dari mana mau ke mana, Mbak?” Hidungnya yang mungil mengembang saat menoleh ke arahku. Pipinya merona sendiri, menjadi satu-satunya pemandangan yang cerah kontras dengan kelam kelabunya hujan. Bibir dengan garis senyum di ujungnya itu berucap, “dari atas hendak ke sini saja, Mas.” Atas? Entah dia merujuk pada bagian utara kota ini yang berada di kaki bukit, atau dari gedung perkantoran bertingkat di ujung jalan, atau malah betulan ‘atas’ seperti atap, langit, atau puncak pohon?
“Atas?”
“Iya.”
“Atas kota? Lantai atas? Atau atas pohon?” tanyaku setengah berkelakar.
Dia tidak menjawab. Sial.
“Oh…ehm, apa yang kiranya Mbak cari?” tanyaku lagi.
“Jodoh.”
“Di teras depan minimarket?”
“Barangkali.”
Sial kuadrat. Rupanya dia bukan tukang ngobrol. Aku pun ikut diam. Berusaha tidak peduli walaupun mati-matian menahan penasaran atas bajunya yang tidak pernah basah kuyup. Urusan bahwa dia menawan itu lain lagi — aku bukannya tidak tertarik, tapi keanehan yang menggantung di belakang kepala lebih darurat untuk dituntaskan.
Dan besoknya dia datang kembali, di waktu yang sama, dengan kecipak yang sama, dan baju yang tidak pernah terlihat basah seluruhnya.
Hingga terik itu datang. Aku sengaja mampir ke teras minimarket itu hingga petang turun. Dia tidak datang. Berhari-hari aku melakukannya. Menunggu. Menuntaskan rasa penasaranku. Nasib memang tukang komplot paling menyebalkan. Hampir tutup musim dan bodohnya, aku masih mampir ke teras minimarket itu hingga petang turun.
Kemudian, dia datang kembali. Lebih tepatnya, aku melihatnya sudah menunggu di teras minimarket saat aku pulang kerja. Aku bergegas, nampaknya tergesa-gesa dan terlihat terlampau antusias. Dia menaikkan alisnya dan terkekeh lirih lalu menegurku, “Nungguin, Mas?”
Aneh. Seakan dia sudah tahu aku melakukan ritual bodoh berkalang bulan. Wajahnya yang merona tampak iseng. Aku tergagap menjawab, “he eh.” Bodoh. Aku tampak bodoh.
Kemudian, tawanya lepas. Petang enggan segera turun, malah semakin terik. Saga di langit menolak merah keunguan, malah berdenyar jingga kekuningan. Senyumnya adalah senyum di mana pelangi keluar dari lesung-lesung nasib buruk. Barisan giginya menggaungkan pengharapan. Aneh sekali.
“Mas mau keluar makan malam?”
Aku bengong. Semoga dia tidak cuma bertanya. “Iya, ini baru pulang kantor, Mbak. Lapar.”
“Ayo makan malam bareng saya aja, Mas.”
Petang jadi turun. Nyala lampu jalan menutupi wajahku yang menyala kemerahan. Dia begitu aneh. Kita berbincang dan langit tidak lain cerah belaka. Mengobrol dengannya membuatku yakin dia lebih dari sekadar riil, dia ethereal. Rautnya begitu ilahi dengan kesenduan yang dijaga sendiri. Tetap saja, ada yang tidak jenak. Dia datang tanpa hujan.
Dia hilang besoknya. Teras minimarket tidak lagi dia tunggui. Aku juga tidak lagi mampir belakangan ini. Sehari, dua hari, tiga hari saja aku sempat mampir dan menunggu hingga petang turun. Di hari ketiga, aku bergegas pulang tidak menunggu gelap. Musim terik hampir habis.
Hari pertama musim penghujan, aku menggunakan pakaian terbaikku untuk berangkat kerja. Aku mampir membeli cincin saat makan siang. Aku sengaja tidak bawa payung. Benar saja, hujan mengguyur tepat saat aku berjalan pulang dari kantor. Aku berteduh di teras minimarket itu. Hujan semakin deras dan rapat. Lalu, aku melihat sosoknya dari balik badai. Mendengar kecipaknya yang familiar, aku mengedarkan pandangan mencari tempat kering untuk bersimpuh di atas satu lutut.


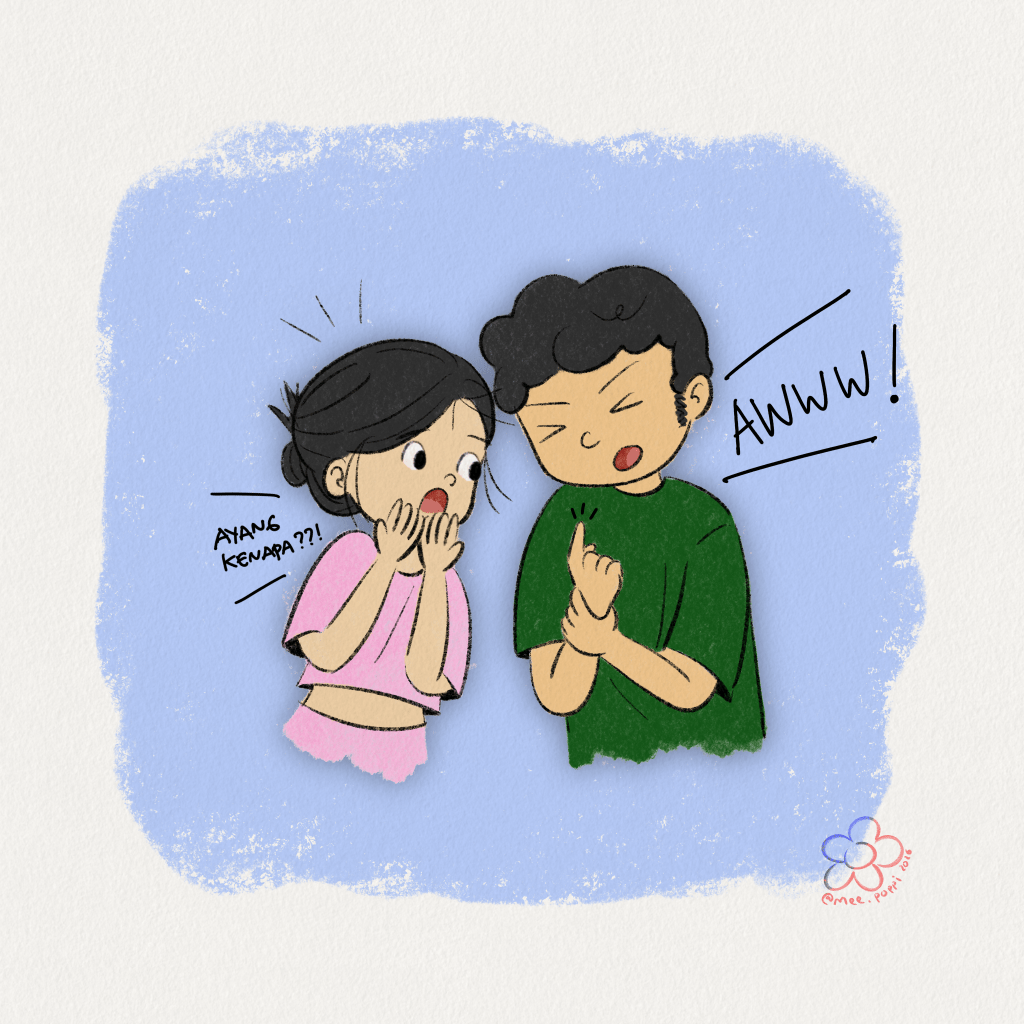


Leave a comment