dialihbahasakan dari The Man-Made World; or, Our Androcentric Culture (1914), karya sosiologis tentang kondisi dan pandangan perempuan gubahan Charlotte Perkins Gilman.
Bagian Pertama: Mengenai Ke-manusia-an[1]
Mari kita mulai, tanpa menyinggung, dengan domba. Domba adalah binatang yang kita semua tahu, banyak digunakan dalam citra religius; jatah wajar bagi para pelukis; bahan pokok dari makanan sehari-hari; satu dari bahan-bahan utama pakaian kita; dan simbol sehari-hari untuk rasa takut dan kebodohan.
Di beberapa daerah berumput, domba merupakan wujud dari teror itu sendiri, menghancurkan rumput, semak, dan hutan dengan menggerigiti terus-menerus di mana-mana; pada dataran yang luas, menggembala seringkali menghasilkan kegilaan, menerbitkan rasa sepi si penggembala, sebab penampakan dan perilaku monoton para domba.
Oleh para penyair, domba muda banyak dirujuk, domba yang berlari dan melompat dengan gembira; kecuali dalam himne-himne, di mana “kita semua seperti domba” berulang-ulang dijelaskan, dan banyak ditekankan pada kecenderungan mengelana si domba.
Bagi kepala-kepala ilmiah ada ketertarikan khusus pada kemanutan para domba, kebiasaan mereka untuk mengikuti satu sama lainnya dengan kemiripan otomatis. Insting ini, kita amati, telah berkembang sekian lama oleh balapan liar berhimpitan pada celah sempit, sepanjang tebing, lubang, sekitar bebatuan yang menjorok dan sudut-sudut, hanya sang pemimpin yang dapat melihat kapan, di mana, dan bagaimana cara meloncat. Jika mereka yang di belakangnya lompat sebagaimana dia melompat, mereka selamat. Jika mereka berhenti untuk melakukan pengamatan sendiri, mereka akan terdorong dan mati; mereka dan pengamatan mereka.
Semua hal ini, dan banyak hal yang mirip, muncul tatkala kita berpikir mengenai domba. Mereka juga betina dan jantan. Ya, sungguh; tapi apa masalahnya? Semua yang sudah dikatakan adalah tentang domba, genus ovis, binatang yang menjemukan itu, penuh dengan daging, wol, dan kedunguan yang begitu terkenal. Jika kita berpikir tentang anjing penggembala, penggembala, dan burung-burung ganas pemakan gibas dari Selandia Baru, yang disebut Kea, semuanya menuntun, menjaga, atau membunuh si domba, baik jantan maupun betina. Dengan mempertimbangkan daging, wol, dan karakter umumnya, kita hanya berpikir tentang ke-domba-an, sama sekali tidak terlintas soal kejantanan atau pun kebetinaan. Apakah gibas atau lembu, anjing, kucing atau kuda, semuanya mudah dikenali sebagai spesies binatang yang disebutkan, dan tidak punya hubungan apa pun soal jenis kelamin dalam mengenalinya.
Kembali ke perkara domba-domba kita, mari cermati domba jantan, dan karakter apa yang membedakannya dengan domba pada umumnya. Kita menemukan bahwa dia mempunyai karakter yang begitu menyebalkan. Dia menghentak bumi dan berbuat bising. Dia punya kecenderungan untuk menyeruduk. Begitu juga seekor kambing—Tuan Kambing. Begitu juga Tuan Kerbau, dan Tuan Rusa Besar, dan Tuan Menjangan. Kecenderungan untuk melontarkan kepala terlebih dahulu kepada musuh ini—dan menengarai setiap jantan lain sebagai musuh dalam jarak pandang—terbukti tidak saja berlaku pada domba, pada genus ovis; namun kepada setiap makhluk jantan bertanduk.
Mengingat “fungsi sebelum organ,” kita bahkan mungkin diberikan sekilas pengingat mengenai rute panjang evolusi, dan melihat bagaimana sesederhana tindak menyeruduk—dengan segenap hasrat dan terus menerus berulang—lahir dari jiwa-jiwa rusuh para jantan—menciptakan tanduk!
Para betina, di sisi lain, menunjukkan kasih dan sayang untuk anak-anaknya, memberi mereka susu dan berupaya melindungi mereka. Namun begitu pula seekor kambing—Nyonya Kambing. Begitu pula Nyonya Kerbau dan lainnya. Terbukti bahwa insting keibuan ini tidak khusus terdapat pada genus ovis, melainkan pada setiap makhluk betina.
Bahkan burung-burung, walau bukan mamalia, menunjukkan kasih-ibu dan sayang-ibu yang sama, sementara para bapak burung, pun tidak menyeruduk, masih berkelahi dengan paruh dan sayap dan taji. Kompetisi mereka lebih efektif melalui tampilan. Keinginan untuk membahagiakan, kebutuhan untuk menyenangkan, kebutuhan menyesakkan atasnya sehingga mereka mengamankan pamrih dari para betina, membuat burung-burung jantan mengembang seperti kupu-kupu. Mereka menyala dengan bulu-bulu yang cantik, mengangkat jengger dan ekornya dengan angkuh, memperlihatkan pial terkulai dan gumpal lemas seperti yang tampak pada kalkun; bulu-bulu halus yang panjang untuk riasan murni tampil padanya; apa yang berada pada para betina hanya berupa akibat dari mempunyai ekor menjadikan padanya secarik jubah besar nan berkilau.
Ayam hutan, ayam ternak, merak, dari burung gereja ke burung unta, perhatikan penampilan para pejantannya! Berjalan begitu angkuh dan tidak nyaman; untuk menampilkan setiap umpan indah; untuk mengorbankan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, segala hal—demi keindahan—demi para betinanya—merupakan watak dari unggas jantan berbagai spesies; karakteristiknya, tidak hanya dari kalkun, melainkan juga dari para jago! Dengan ketukan berisik sayap-sayap mereka, dengan kokok dan gaok dan cericip lagu megah, mereka menggoda pasangan mereka; memperlihatkan kemegahannya di depan mereka; bertarung tanpa takut melawan saingannya. Menyereduk—berkotek—membuat bising—semua demi cinta; tindak-tanduk ini biasa saja bagi para pejantan.
Sekarang kita mungkin menggeneralisir dan jelas-jelas menyatakan: Bahwa menjadi maskulin dimiliki para pejantan—kepada setiap atau semua pejantan, terlepas dari spesiesnya. Sementara menjadi feminin dimiliki para betina, kepada setiap atau semua betina, terlepas dari spesiesnya. Adalah gibas, lembu, kucing, anjing, kuda atau keledai yang tergabung dalam spesies tersebut, terlepas dari jenis kelaminnya.
Dalam spesies kita sendiri semua hal ini berubah. Kita telah begitu terlibat dengan fenomena maskulinitas dan feminitas, sehingga kemanusiaan bersama menjadi luput dari perhatian. Kita tahu kita adalah manusia, secara alami, dan kita menjadi sangat bangga akan hal tersebut; namun kita tidak mempertimbangkan dalam pasal apa kemanusiaan kita terbentuk; atau tidak berpikir tentang bagaimana para laki-laki dan perempuan mungkin belum mencapai kemanusiaan itu sendiri, atau melangkahi batas-batasnya, dan kengototan terus menerus atas perbedaan khusus masing-masing. Adalah “laki-laki banget” melakukan ini; adalah “perempuan sekali” melakukan itu; namun apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia dalam keadaan-keadaan tertentu luput dipikirkan.
Kesempatan langka ketika kita menyadari apa yang kita sebut “kemanusiaan pada umumnya” adalah dalam kasus-kasus ekstrem, melibatkan persoalan hidup dan mati; Ketika baik laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berlaku seolah mereka juga makhluk manusia. Mengingat rentang perasaan dan tindakan yang pantas untuk kemanusiaan, jauh lebih luas dari pada yang pantas untuk kedua jenis kelamin, sekilas betapa kita hanya sedikit sekali mengakuinya.
Sedikit klasifikasi mungkin akan membantu kita. Kita mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang mirip dengan benda mati, seperti berat, kekasatan, dan ketahanan. Jelas-jelas hal ini bukan manusia. Kita mempunyai kualitas lain yang mirip dengan bentuk kehidupan lain; konstruksi seluler, contohnya, reproduksi sel dan kebutuhan akan nutrisi. Lagi-lagi hal ini bukan manusia. Kita mempunyai hal lain, banyak hal lain, yang mirip dengan mamalia tingkat tinggi; yang tidak kita miliki saja—bukan “manusia” secara khusus. Lalu apa sebenarnya karakteristik manusia sejati? Dengan cara apa spesies manusia dibedakan dari spesies lainnya?
Ke-manusia-an kita dapat dilihat dengan jelas dalam tiga batas: yang mekanis, psikis, dan sosial. Daya kita untuk membuat dan menggunakan benda-benda pada dasarnya adalah manusia; kita sendiri mempunyai alat-alat ekstra-fisik. Kita telah menambahkan untuk gigi-gigi kita pisau, pedang, gunting, mesin pemotong; untuk cakar-cakar kita sekop, garu, bajak, bor, keruk. Kita adalah makhluk paripurna, menggunakan daya otak lebih besar melalui berbagai jenis senjata yang berubah-ubah. Ini merupakan pembeda yang penting dan utama dari kita. Ras hewan kuno terlacak hanya melalui tulang dan cangkang, ras manusia kuno melalui bangunan, alat, dan perlengkapannya.
Tingkat perkembangan yang memberikan kita akal manusia adalah pembeda ras yang jelas. Hewan buas yang dapat berhitung hingga seratus jauh lebih manusiawi ketimbang hewan buas yang dapat berhitung hingga sepuluh.
Lebih tampak lagi ketimbang dua hal tersebut adalah bakat sosial dari kemanusiaan. Kita bukanlah satu-satunya hewan dengan kerumunan; tipe indutri kuno bangsa semut, dan bahkan bangsa lebah yang tua, adalah makhluk-makhluk sosial. Namun serangga-serangga dari golongan mereka dapat ditemukan hidup sendiri. Manusia tidak akan pernah. Ke-manusia-an kita bermula dari bentuk rendah relasi sosial dan meningkat bersamaan dengan berkembangnya relasi tersebut.
Kehidupan manusia jenis apa pun bergantung pada apa yang Kropotkin sebut sebagai “gotong royong,” dan kemajuan manusia melangkah mantap dengan adanya pertukaran jasa terahlikan yang menggerakkan masyarakat menjadi organik. Para nomaden, hidup dalam lingkung sebagaimana semut-semut hinggap di sarangnya, tidak lebih manusia ketimbang para petani, menumbuhkan makanan dengan usaha cerdas yang diaplikasikan; dan perluasan pertukaran dan perdagangan, dari pasar-pasar desa hingga pertukaran global saat ini, adalah perluasan ke-manusia-an pula.
Kemanusiaan, jika dipikir-pikir, bukanlah sesuatu yang suatu waktu dibuat dan tidak berubah, melainkan sebuah tahapan perkembangan; dan masih akan terus berkembang, sebagaimana Wells menjelaskan hal ini sebagai, “dalam kemenjadian.” Ke-manusia-an kita tampaknya tidak begitu terletak pada masing-masing diri kita, lebih kepada hubungan kita ke satu sama lainnya; dan bahkan pula individualitas tidak lain merupakan hasil dari hubungan kita terhadap satu sama lainnya. Hal ini terletak pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, ketimbang pada apa kita sebenarnya. Beberapa kecenderungan filosofis memang mengagungkan “kemenjadian” alih-alih “kekaryaan.” Bagi mereka pertanyaan ini dapat diletakkan sebagai berikut: “Dapatkah anda menyebutkan bentuk kehidupan yang hanya ‘mengada,’ tanpa melakukan apa pun?”
Jika ditengok secara terpisah dan secara fisik, kita adalah hewan, genus homo; jika ditengok secara sosial dan psikis, kita, dalam berbagai tingkatan, adalah manusia; dan sejarah kita yang sebenarnya terletak pada perkembangan ke-manusia-an ini.
Periode kesejarahan kita sebenarnya belum berlangsung lama. Sejarah yang benar-benar tertulis baru bermula dalam beberapa ribu tahun terakhir, dimulai dengan prasasti Mesir kuno. Selama periode ini kita mempunyai apa yang sekarang secara universal disebut Kebudayaan Androsentris. Sejarah, sebagaimana yang sudah-sudah, dibuat dan ditulis oleh para lelaki.
Perkembangan mental, mekanis, dan sosial hampir seluruhnya milik mereka. Kita, sejauh ini, hidup dan menderita dan mati di dunia yang dibentuk-lelaki. Kondisi ini berlangsung begitu umum, begitu geming, bahkan sekadar menyebutnya menimbulkan pernyataan soal hukum alam belaka. Kita telah begitu mapan dengan konsep tersebut, sejak mula peradaban, bahwa “jenis manusia” (mankind) berarti jenis laki-laki (men-kind), dan dunia adalah milik mereka.
Perempuan yang kita punya telah begitu dijatuhkan. Perempuan hanyalah jenis kelamin (sex), “persetebuhan” (sex) bahkan, menurut persulangan para laki-laki yang paling sopan; perempuan dibedakan untuk layanan khusus yang khas dari femininitas. Sebagaimana seorang ilmuwan Inggris pada 1888 menyatakan, “Perempuan tidak saja bukanlah sebuah ras—mereka bahkan tidak setengahnya, melainkan subspesies yang diperintah untuk berkembang biak belaka.”
Sikap mental terhadap perempuan ini lebih gamblang lagi dinyatakan oleh H. B. Marriot-Watson dalam artikelnya mengenai “Perempuan Amerika” di “Abad Kesembilan belas” pada Juni 1904, di mana dia menulis: “Kegelisahan pokok para perempuan telah menghilangkan fungsi-fungsi mereka, hal begitu saja telah mengizinkan dan menjelaskan eksistensi mereka.” Ekspresi yang begitu ringkas dan anehnya bahagia ini berbincang soal posisi relatif perempuan dalam kebudayaan androsentris kita. Para laki-laki diterima sebagai tipe ras tanpa keberatan sama sekali; dan para perempuan—makhluk yang begitu beragam dan aneh, begitu sumbang dalam skema penerimaan—diizinkan dan dijelaskan sebagai betina semata.
Para perempuan telah begitu muak akan alasan dan penjelasan tersebut; tampaknya juga, muak akan kekerasan dan kutukan. Dalam berbagai katalog perpustakaan kita dapat menemukan berbagai buku mengenai perempuan: fisiologis, sentimental, didaktik, relijius—berbagai macam buku mengenai perempuan, dengan nada demikian. Bahkan hari ini dalam karya-karya Marholm—Weininger muda merana, Moebius, dan lain-lain, kita menemukan diskusi yang berulang-ulang soal perempuan—dengan nada demikian.
Buku ini adalah buku tentang laki-laki—dengan nada demikian. Di sini membincangkan perbedaan antara tabiat manusia dan tabiat jenis kelamin. Tentu buku ini tidak akan sejauh itu menuduh sifat maskulin laki-laki sebagai pelaziman atau penjelasan keberadaan mereka: namun buku ini akan menunjukkan apa yang membedakan sifat maskulin dan sifat kemanusiaan, dan apa yang telah menjadi akibat dari kehidupan manusia dengan satu jenis kelamin mempunyai dominasi tak terkendali.
Kita dapat melihat, terang benderang, apa jadinya jika kita menyerahkan semua urusan manusia ke tangan perempuan. Keadaan yang luar biasa dan celaka akan mem’feminisasi’ dunia. Kita semua harusnya berlaku “keperempuan-perempuanan.”
Lihat bagaimana kita menggunakan bahasa, kasus tersebut jelas-jelas diperlihatkan. Kata sifat dan kata turunan berdasarkan perbedaan yang ada pada perempuan adalah begitu asing dan melecehkan jika disematkan pada urusan manusia; “keperempuan-perempuanan” (effeminate), atau secara kasar, banci—terlalu betina, berkonotasi menghina, tapi tidak punya padanan untuk maskulin; bahkan “melemahkan” (emasculate)—kurang jantan, merupakan istilah celaan, dan tidak punya padanan feminin. “Jantan” (virile)—konotasi keperkasaan, dilawankan dengan “kekanak-kanakan” (puerile), dan kata “kebajikan” (virtue) diambil dari vir—laki-laki.
Bahkan saat menamai hewan lain, kita menyematkan jantan sebagai tipe ras, dan meletakkan akhiran khusus untuk menunjukkan “betinanya,” seperti singa (lion) dan singa betina (lioness); macan tutul (leopard), macan tutul betina (leopardess); sementara semua skema manusia kita bersandar pada asumsi mapan; pria (man) untuk menyebut jenis manusia; wanita (woman) menjadi bagian dari sejawat dan asisten bawahan, hanya penting untuk berkembang biak belaka.
Perempuan selalu ditempatkan sebagai preposisi dalam relasinya dengan laki-laki. Perempuan selalu disebut di atasnya atau di bawahnya, sebelumnya, belakangnya, sampingnya, benar-benar eksistensi keterhubungan semata—“saudarinya Anu,” “ibunya Fulan”—namun tidak pernah dirujuk sebagai Anuwati atau Fulanah itu sendiri.
Berangkat dari asumsi berikut, semua standar manusia telah begitu tersandar pada karakteristik pria, dan ketika kita akan memuji karya seorang wanita, kita akan berkata “dia punya otak yang sangat maskulin.”
Bukan hal mudah untuk menolak atau membalik asumsi universal. Pikiran manusia telah mengalami banyak sekali kejutan sejak dapat berpikir, tapi setiap setelah gejolak ia akan kembali jenak sebagaimana para petani anggur di Vesuvius, yang menerima bahwa kerak lava terakhir telah menjadi tanah permanen.
Apa yang secara kasat kita lihat, yang kita dilahirkan ke dalamnya dan tumbuh bersamanya, entah kelengkapan mental atau fisik, kita asumsikan sebagai tata aturan alam itu sendiri.
Jika sebuah ide yang mapan dalam kepala manusia pada banyak generasi, hampir seawam ide-ide yang kita punya sekarang, untuk menyingkirkannya kita akan membutuhkan usaha terus menerus dan legawa; dan jika ide tersebut merupakan ide yang sangat tua, yang sangat besar, sangat awam, ide-ide yang mapan secara universal, betapa keras kerja-kerja yang dibutuhkan bagi siapa-siapa yang berniat mengubahnya.
Bagaimana pun, jika masalah yang diangkat merupakan masalah penting, jika ide-ide terdahulu begitu gamblang kesalahannya, mempunyai akibat yang besar dan jahat, dan jika ide yang baru adalah benar belaka dan sangat berguna, maka usaha tersebut berharga untuk dijalankan.
Buku ini berusaha melaksanakan tugas tersebut. Penjabaran di sini berusaha menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita sebut “tabiat manusia” dan konsep usang, tidak lain sebagian besarnya merupakan tabiat laki-laki, yang mana cocok-cocok saja jika diletakkan pada tempatnya; bahwa apa yang kita sebut sebagai “maskulin” dan kekaguman atasnya, sebagian besarnya merupakan manusiawi belaka, dan selayaknya disematkan pada kedua jenis kelamin: bahwa apa yang kita sebut sebagai “feminin” dan tercela, juga sebagian besarnya manusiawi dan dapat disematkan kepada kedua jenis kelamin pula. Kebudayaan androsentris kita telah menunjukkan, dan masih akan menunjukkan, ekses-ekses budaya maskulin, dan maka dari itu tidak lagi diinginkan.
Dalam karya-karya lawas yang mendekati fakta-fakta ini akan dengan mudah menjelaskan betapa kesalahan-kesalahan yang begitu akut dan serius secara praktis telah dilakukan oleh semua laki-laki. Alasannya sesederhana karena mereka jantan, bersikeras melihat perempuan sebagai betina—dan bukan sebaliknya.
Keyakinan seperti itu begitu absolut sehingga laki-laki yang membaca ini akan berseru, “Tentu saja! Bagaimana lagi kami memandang para wanita kecuali sebagai betina? Mereka benar betina, bukan?” Ya, benar, sebagaimana para pria adalah jantan; namun bertahan pula kemungkinan bahwa kerangka pikir dari tuan tanah kuno yang ditanya oleh rekan Inggrisnya soal bagaimana bisa perempuan mempunyai seorang pelayan bujang melayani sarapan di ranjangnya—untuk melihat laki-laki lain di kamar tidurnya—dan menjawab dengan sungguh-sungguh, “Kamu menganggapnya laki-laki itu manusia?”
Dunia sungguh dipenuhi para laki-laki, tapi kedudukan utama mereka merupakan sejenis kekaryaan manusia; dan para perempuan melihat adanya perbedaan manusiawi yang besar dalam diri laki-laki. Dalam beberapa kesempatan para nyonya murung mengawini kusirnya—bahu-bahu lebar yang terus menerus ditatap barangkali menjadi sebab; namun secara umum para perempuan melihat makhluk manusiawi belaka; dan makhluk jantan hanya saat mereka jatuh cinta.
Bagi para laki-laki, seluruh dunia adalah miliknya; miliknya karena dia adalah pejantan; dan rumah merupakan seluruh dunia bagi para perempuan; karena mereka betina. Perempuan mempunyai lingkup yang ditentukan, benar-benar terbatas oleh kedudukan dan ketertarikan femininnya; para laki-laki mempunyai seluruh sisa dari kehidupan; dan tidak hanya itu, tapi, sudah dipunyai pun, masih bersikeras menyebutnya jantan.
Hal ini termasuk sikap umum laki-laki atas humanisasi perempuan yang sedang kencang-kencangnya di masa sekarang. Sejak perjuangan pertama perempuan akan kebebasan dan keadilan yang sembunyi-sembunyi, hingga usaha terang-terangan dan berani untuk menuntut kesetaraan ekonomi dan politik secara penuh di masa kini, tiap langkahnya telah dicap sebagai “kurang feminin” dan dicibir sebagai pembobolan akan kuasa dan ruang laki-laki. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan klasifikasi baru, dari tiga bidang kehidupan yang berbeda-beda—maskulin, feminin, dan manusia.
Malah, terdapat “lingkup perempuan,” yang jelas-jelas dibedakan dari ruang laki-laki; ada pula “lingkup laki-laki,” yang jelas-jelas dibedakan dan lebih terbatas; namun terdapat pula lingkup umum—dari kemanusiaan, yang dipunyai oleh keduanya.
Dalam babak-babak awal “gerakan perempuan,” perlawanan begitu keras atas landasan bahwa perempuan kelak menjadi “tidak berkelamin.” Mari kita catat sepintas bahwa mereka telah menjadi tidak berkelamin dalam satu hal, jelas-jelas, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan atau keberatan.
Sebagai bagian dari budaya androsentris, kita perlu menunjuk pada pembalikan khusus dari karakteristik jenis kelamin yang membuat manusia betina memanggul beban sebagai hiasan. Perempuan sendiri, dari semua makhluk manusia, telah mengadopsi atribut maskulin dasar dari dekorasi-seks khusus; ia tidak bertarung untuk pasangannya, tapi ia mengembang sebagaimana merak dan cendrawasih, dalam pembalikan menyedihkan hukum alam, bahkan mengenakan bulu-bulu maskulin untuk memperpanjang buntut femininnya.
Kerja alami para wanita sebagai betina adalah sebagai ibu; kerja alami para pria sebagai pejantan adalah sebagai ayah; relasi setara mereka pada akhirnya menjadi sumber kebahagiaan dan kesentosaan jika dijalankan dengan benar: namun kerja-kerja manusia meliputi seluruh kehidupan di luar kekhasan tersebut. Setiap kerajinan, setiap profesi, setiap ilmu pengetahuan, setiap seni, semua rekreasi dan kesenangan normal, semua pemerintahan, pendidikan, agama; semua dunia pencapaian manusia yang hidup: semuanya adalah manusiawi belaka. Satu jenis kelamin yang memonopoli semua aktivitas manusia, menyebutnya “kerja-kerja pria,” dan mengaturnya sedemikian rupa, adalah apa yang dimaksud dengan frasa “Kebudayaan Androsentris.”
[1] Human-ness bisa juga merupakan permainan kata (plesetan atau pun) dengan menambahkan sufiks –ess yang menandakan versi perempuan dari sesuatu—penerjemah.


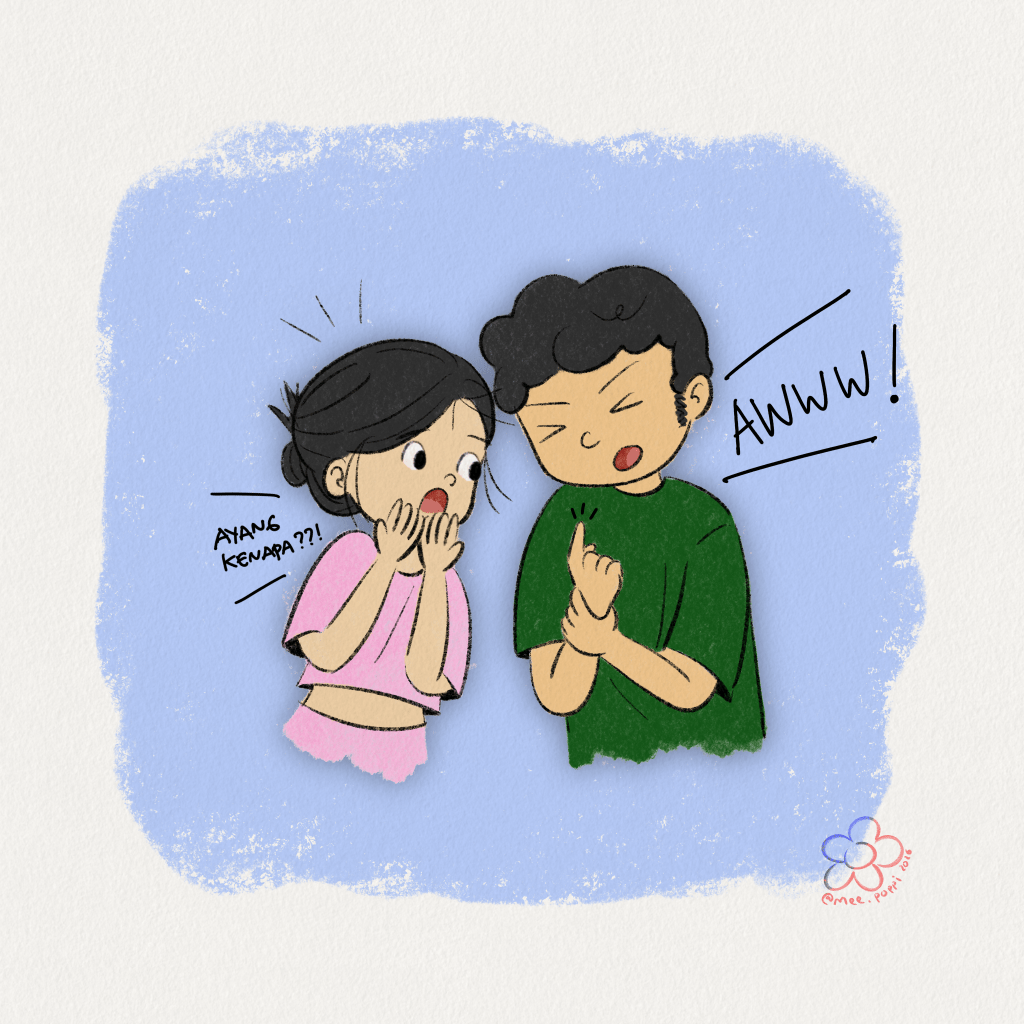


Leave a comment