Diterjemahkan dari Letter of His Holiness Pope Francis on the Role of Literature in Formation.
- Pada mulanya saya memilih judul yang merujuk kepada pembinaan imamat untuk Surat ini. Namun, setelah direnungkan kembali, bahasan ini dapat diterapkan pula pada segenap pembinaan bagi mereka-mereka yang mengabdi di bidang kepastoran, bahkan bagi seluruh pengikut Kristus. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pentingnya membaca novel dan puisi sebagai jalan untuk kedewasaan diri.
- Seringkali pada rentang yang membosankan saat liburan, di lingkungan yang panas menyengat serta sunyi, menemukan buku yang bagus adalah laiknya menemukan oasis yang menjaga kita dari pilihan tindakan lain yang kurang patut. Pun sama, di kala letih, murka, kecewa, dan kegagalan, ketika doa tak cukup menenangkan batin, buku yang bagus dapat membantu kita meneduhkan badai hingga kita menemukan ketenangan pikiran. Waktu yang dihabiskan untuk membaca mungkin malah membukakan ruang batin yang membantu kita untuk menghindari jebakan pikiran-pikiran obsesif yang menghalangi pertumbuhan diri kita. Sebelum masa kiwari yang dipenuhi gejolak media sosial, ponsel, dan gawai lain, membaca merupakan pengalaman yang biasa dimiliki, dan mereka yang telah menjalaninya mengerti apa yang saya maksud. Membaca bukanlah hal yang benar-benar kuno.
- Tidak seperti media audio-visual, di mana produknya lebih ‘merdeka’ (self-contained) dan waktu yang diizinkan untuk ‘memperkaya’ wacana atau menjelajahi kegunaannya biasanya cukup terbatas, buku meminta keterlibatan yang lebih personal dari para pembacanya. Pembaca dalam nalar tertentu, menulis ulang teksnya, memperbesar cakupannya melalui imajinasi mereka, menciptakan dunia yang utuh dengan membawa segenap kemampuannya. Dalam hal ini, apa yang muncul adalah sebuah teks yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Sebuah karya sastra maka menjadi teks yang hidup dan terus berbuah, selalu mampu untuk berbicara dengan cara-cara yang berbeda dan menciptakan sintesis asli di kepala setiap pembacanya. Dalam pembacaan kita, kita diperkaya oleh apa yang kita terima dari sang penulis dan mengizinkannya untuk tumbuh ke dalam diri, sehingga pada setiap karya yang kita baca akan selalu terbarukan dan memperluas pandangan kita.
- Karena alasan inilah, saya sangat mengapresiasi tindak sebagian seminari yang telah bereaksi atas fenomena obsesi akan ‘layar’ yang membawa berita-berita bohong yang penuh kekerasan, palsu, dan beracun, dengan membaktikan waktu serta perhatiannya pada sastra. Mereka telah menerapkannya dengan menyisihkan waktu untuk membaca sunyi dan berdiskusi soal buku, baru dan lawas, yang terus menerus berbicara banyak kepada kita. Maka, perlu disesali, pergumulan yang cukup dengan sastra secara umum belum menjadi bagian dari program pembinaan bagi pelayanan tahbisan. Sastra acapkali dianggap sebagai bentuk hiburan semata, ‘seni minor’ yang tidak punya tempat dalam pendidikan dan persiapan para calon pendeta untuk pelayanan pastoral. Kecuali sedikit, sastra dianggap tidak esensial. Saya berpikir bahwa hal penting untuk ditekankan adalah betapa tidak sehatnya pemikiran tersebut. Pemikiran tersebut bisa mendorong pemiskinan intelektual dan spiritual yang serius bagi para calon pendeta, yang nantinya bakal kekurangan akses mewa yang disediakan oleh sastra untuk menuju ke jantung kebudayaan manusia dan, lebih khususnya, jantung setiap manusia.
- Dengan surat ini, saya ingin menawarkan perubahan radikal dalam pendidikan. Dalam hal ini, saya sepakat dengan pengamatan salah satu teolog yang berkata, “sastra…yang bermula di inti hati manusia yang tidak dapat dikerdilkan, tingkat yang tak-terjelaskan [dari ke-ada-an mereka]…Sastra adalah hidup itu sendiri, yang mawas atas dirinya sendiri, yang telah menggapai kepenuhan ekspresi dirinya lewat pemanfaatan atas sumberdaya konseptual akan bahasa”.1
- Maka sastra, dalam satu cara atau lainnya, punya keterkaitan dengan hasrat terdalam kita dalam kehidupan ini, mengingat bahwa sastra di tingkat agung menyentuh eksistensi konkret kira, dengan tegangan-tegangan bawaannya, hasrat-hasrat serta pengalaman yang penuh makna.
- Saat masih menjadi guru muda, saya mendapati sastra demikian bersama murid-murid saya. Di rentang 1964 dan 1965, di umur 28, saya mengajarkan sastra di Sekolah Jesuit di Santa Fe. Saya mengajar kelas tengah dan senior di sekolah menengah atas dan mewajibkan para siswa untuk membaca El Cid. Para murid tidak senang; mereka malah meminta untuk membaca García Lorca. Maka saya memutuskan mereka bisa membaca El Cid di rumah, dan ketika pelajaran berlangsung saya mendiskusikan para penulis yang digandrungi oleh para siswa. Tentu saja, mereka lebih menyenangi karya sastra kontemporer. Pun begitu, sembari mereka membaca apa yang mereka senangi saat itu, mereka turut mengembangkan selera sastra dan puisi, agar kemudian mereka berpindah ke penulis lain. Pada akhirnya, hati kita akan selalu mencari sesuatu yang lebih agung, dan orang-perorang akan menemukan jalan mereka dalam susastra.2 Saya sendiri lebih menyukai para penulis tragedi, karena kita dapat merengkuh karya mereka sebagai milik kita sendiri, sebagai ungkapan atas drama kita sendiri. Ketika menangisi nasib para karakternya, naluriahnya kita menangisi diri kita sendiri, menangisi kekosongan, cela, dan kesendirian. Tentu, saya tidak meminta anda untuk membaca buku yang sama dengan saya. Setiap orang akan menemukan buku yang berbicara mewakili kehidupannya, yang menjelma pendamping otentik atas perjalanan mereka. Tidak ada yang lebih kontraproduktif daripada membaca karena merasa diwajibkan, mengeluarkan segenap upaya semata karena orang lain bersabda tentang pentingnya buku tersebut. Di sisi lain, sembari membuka diri pada teladan atau pedoman, kita harusnya memilih bacaan kita dengan pikiran terbuka, mempersilakan diri untuk terkejut, kelenturan tertentu serta kesiapan untuk belajar, mencoba menggali apa yang sebenarnya kita butuhkan di setiap titik kehidupan ini.
Iman dan budaya
………………………………………………………………………… - Sastra terbukti penting pula bagi mereka yang beriman dan secara tulus ikhlas mencari jalan masuk ke dalam dialog kebudayaan di masa mereka, atau hanya ke dalam hidup serta pengalaman orang lain. Dengan alasan yang mumpuni, Konsili Vatikan II telah mengamati bahwa, “sastra dan seni…telah merasuki tabiat kita” dan “menyingkap celaka dan bahagia, kebutuhan dan kekuatan kita.”3 Sastra memang mengambil bentuknya dari realitas sehari-hari kita, hasrat-hasrat serta peristiwanya, “tindakan, karya, cinta, kematian, dan hal-hal remeh yang memenuhi hayat.”4
- Bagaimana bisa kita menggapai jiwa kebudayaan lawas dan baru jika kita tidak berusaha mengenali, mengabaikan dan tidak mengacuhkan simbol-simbol, pesan, ungkapan artistik kebudayaan dan hikayat-hikayat yang telah merekam dan membangkitkan ideal dan aspirasi mahaluhur, sebagaimana hikayat tersebut telah merekam pula penderitaan, ketakutan, dan hasrat kebudayaan? Bagaimana kita bisa berbincang dari hati ke hati segenap manusia jika kita mengabaikan, meminggirkan, atau gagal mengapresiasi ‘hikayat-hikayat’ di mana manusia menemukan jalannya untuk mengungkapkan dan menelanjangi pengalaman hidupnya dalam novel-novel dan puisi-puisi?
- Sang Gereja, dalam pengalaman dakwahnya, telah belajar untuk menampilkan segala bentuk keindahannya, kebaruan dan kesegaran dalam pertemuan-pertemuannya—seringnya melalui sastra—dengan kebudayaan-kebudayaan berbeda di mana iman telah mengakar, tanpa ragu melibatkan diri dan mengambil apa yang menurutnya terbaik di setiap kebudayaan. Pendekatan ini telah membebaskan Sang Gereja dari godaan perujukan kembali yang fundamentalis nan terbatas yang lebih menyukai ‘tata-aturan’ kebudayaan-sejarah tertentu sebagai satu ungkapan yang mampu menafsirkan seluruh kakayaan dan kedalaman Injil.5 Kebanyakan ramalan hari akhir yang akhir-akhir ini lebih suka mencari penderitaan berakar dari keyakinan seperti itu. Bersentuhan dengan langgam sastra serta tata-bahasa yang berbeda akan selalu mempersilakan kita untuk menjelajahi suara wahyu ilahi yang beragam (polifoni) dengan lebih dalam tanpa memiskinkannya atau mereduksinya berdasarkan kebutuhan atau cara berpikir kita sendiri.
- Maka sudah bukan kebetulan lagi jika sejarah Kristiani, sebagai contoh, terang-terangan menyadari kebutuhan akan persentuhan serius dengan budaya klasik di masa tersebut. Basil dari Caesarea, salah satu dari Bapa Gereja Timur, dalam Diskursus bagi Para Pemuda, ditulis antara tahun 370 dan 375, dan kemungkinan besar dialamatkan bagi keponakan-keponakannya, memuji kekayaan sastra klasik yang digubah oleh hoi éxothen (‘yang di luar’), begitulah beliau menyebut para penulis pagan. Beliau melihatnya baik dari sisi argumentasi, di mana, lógoi (diskursus)-nya, berguna bagi teologi dan eksegesis, serta sisi etisnya, dapat disebut sebagai práxeis (tindakan) yang menyumbang makna pada kehidupan moral dan asketis. Basil menutup surat tersebut dengan mendorong para pemuda Kristiani untuk melihat karya klasik sebagai ephódion (‘viatikum’) bagi pembinaan dan pendidikannya, jalan bagi ‘keuntungan jiwa’ (IV, 8-9). Karena dari pertemuan antara Kristianitas dan kebudayaan zaman itulah, sebuah penyampaian pesan Injil yang segar dapat muncul.
- Berkat kearifan injili akan kebudayaan, kita dapat mengenali kehadiran Roh dalam berbagai pengalaman manusia, melihat benih-benih Roh tertanam dalam peristiwa, nalar, hasrat, dan kerinduan mendalam yang hadir di dalam hati dan latar sosial, kultural, dan spiritual. Kita dapat menengok, sebagai contoh, ke dalam pendekatan yang dilakukan oleh Paul di hadapan sidang Areopagus, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul (17: 16-34). Dalam khotbahnya, Paul bersabda tentang Tuhan: “‘Dalam-Nya kita hidup dan bergerak dan mengada’; dan sebagian dari penyair kalian berkata, ‘Kita pun adalah anak-anakNya’.” (Kisah 17: 28). Ayat ini mengandung dua kutipan: kutipan tidak langsung, dari penyair Epimenides (abad keenam SM), dan kutipan langsung, dari Phaenomena penyair Aratus asal Soli (abad ketiga SM), yang turut menulis soal rasi bintang dan prakiraan cuaca buruk serta baik. Di sini, “Paul mengungkapkan dirinya sebagai ‘pembaca’ sekaligus menyingkap metodenya dalam mendekati teks sastrawi, yang mana merupakan kearifan injili akan kebudayaan. Warga Athena mencibirnya sebagai permologos, ‘peracau’, dan secara harfiah, ‘pengepul benih’. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai cacian, secara ironis, punya kedalaman makna yang benar. Paul mengumpulkan benih-benih dari puisi para penganut pagan dan melampaui kesan pertamanya (lihat Kisah 17:16), mengakui warga Athena sebagai warga ‘yang sungguh relijius’ dan melihat halaman-halaman sastra klasiknya sebagai praeparatio evangelica yang jujur.”6
- Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Paul? Beliau mengerti bahwa “sastra membawa cahaya pada jurang gelap di diri setiap insan, sementara wahyu dan kemudian teologi mengambil alih untuk memperlihatkan bagaimana Kristus masuk ke jurang-jurang ini dan meneranginya”.7 Di wajah jurang-jurang ini, sastra kemudian adalah “jalan”8 untuk menolong para gembala jiwa-jiwa memasuki dialog yang membuahkan dengan budaya di zaman mereka.
Bukan Kristus yang tidak menubuh
………………………………………………………………………… - Sebelum menyelami lebih jauh ke dalam alasan-alasan khusus terkait sebab studi sastra harus didukung dalam pembinaan para calon pendeta, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang lanskap keagamaan kontemporer. “Kembalinya yang sakral dan pencarian spiritualitas yang menandai zaman kita adalah fenomena taksa. Hari ini, tantangan kita bukanlah ateisme mengingat kebutuhan yang begitu mendesak untuk secara tepat merespon kerinduan banyak manusia akan Tuhan, agar mereka tidak mencoba mengobati kerinduannya dengan solusi-solusi yang malah menjauhkan atau dengan Yesus yang tidak menubuh”.9 Tugas penting dalam mendakwahkan Injil di zaman kita meminta orang-orang beriman, wa bil khusus para pendeta, untuk memastikan setiap orang dapat melihat Yesus Kristus sebagai daging, sebagai manusia, sebagai sejarah. Kita harus begitu berhati-hati agar tidak meleng dari ke’daging’an Yesus Kristus: daging yang punya hasrat, emosi dan perasaan, kata-kata yang menguji dan menghibur, tangan-tangan yang menyentuh dan menyembuhkan, tatapan yang membebaskan dan membakar jiwa, tubuh yang merawat, memaafkan, memarahi, menguatkan, meneguhkan; dengan kata lain, mencintai.
- Pada tingkat inilah keakraban dengan sastra dapat membuat para calon pendeta dan semua pekerja pastoral lebih sensitif terhadap kemanusiaan yang utuh dari Tuhan Yesus, yang di dalam-Nya pula keilahian. Melalui sastra, mereka dapat mengabarkan Injil dengan cara yang mempersilakan setiap orang untuk mengalami kebenaran dari ajaran Konsili Vatikan II yang menulis, “hanya di dalam misteri Firman yang menjelma daging di mana misteri manusia menjadi terang benderang”.10 Hal ini bukanlah misteri kemanusiaan yang kabur, namun misteri atas segenap manusia, dengan rasa sakit, hasrat, ingatan, dan harapan yang menjadi bagian konkret dari kehidupan mereka.
Kebaikan akbar
………………………………………………………………………. - Dari sudut pandang praktis, banyak ilmuwan menjelaskan bahwa kebiasaan membaca punya dampak positif dalam kehidupan orang-orang, membantu mereka untuk menyerap lebih banyak kosakata dan kemudian mengembangkan kemampuan berwawasan yang lebih luas. Membaca dapat pula merangsang imajinasi dan kreativitas, mempersilakan mereka untuk berlajar menyampaikan hikayat mereka lewat cara-cara yang lebih kaya dan ekspresif. Membaca dapat pula meningkatkan kemampuan mereka untuk berkonsentrasi, mengurangi penurunan kognitif, dan menenangkan cemas dan stres.
- Lebih lagi, membaca menyiapkan kita untuk memahami dan kemudian berhadapan dengan berbagai situasi dalam hidup. Ketika membaca, kita menenggelamkan diri kita dalam pikiran, kekalutan, tragedi, bahaya, dan ketakutan karakter-karakter yang di penghujung cerita berhasil menaklukkan tantangan hidup. Mungkin juga, dengan mengikuti sebuah cerita hingga akhir, kita mendapat wawasan yang terbukti membantu kehidupan kita di kemudian hari.
- Dalam usaha untuk menggalakkan membaca, saya akan menyebut dua teks yang ditulis oleh penulis kondang, yang, dalam sedikit kata, telah banyak mengajari kita: Novel melepas “sesuatu ke dalam diri kita, dalam rentang satu jam, seluruh bahagia dan celaka yang mungkin, yang dalam hidup, mungkin membutuhkan bertahun-tahun hanya untuk merasakan sebagiannya, di mana pengalaman yang paling hebatnya belum tentu mengungkapkan diri kepada kita karena kelambanan pengalaman-pengalaman tersebut untuk muncul menjaga kita dari mengalaminya secara utuh”.11 “Dalam membaca karya sastra akbar saya menjelma seribu orang, pun masih tetap diri saya sendiri. Seperti langit malam di puisi-puisi Yunani, saya melihat dengan seribu mata, namun yang masih saya lihat tidak lain adalah diri saya sendiri. Di sini, sebagaimana dalam pemujaan, dalam pengabdian, dalam tindakan lurus, dan dalam mengetahui, saya melampaui diri saya sendiri; dan saya tidak pernah lebih menjadi diri saya sendiri ketimbang saya menyadari diri saya sendiri”.12
- Bagaimana pun, bukan maksud saya untuk hanya memfokuskan pada kebermanfaatan personal yang dapat diambil dari membaca, melainkan untuk merenungkan alasan-alasan paling penting saat mendorong kecintaan yang terbarukan terhadap membaca.
Mendengar suara liyan
………………………………………………………………………… - Ketika saya memikirkan ihwal sastra, saya teringat oleh sesuatu yang dikatakan oleh penulis luar biasa dari Argentina, Jorge Luis Borges13 kepada murid-muridnya, bahwa hal yang paling penting belaka adalah membaca, untuk memasuki persentuhan langsung dengan dunia sastra, untuk melibatkan diri dalam teks hidup di hadapan kita, alih-alih meributkan komentar-komentar dan ide-ide kritis. Borges menjelaskan petuah ini kepada muridnya dengan mengatakan bahwa pada mulanya mereka mungkin tidak akan begitu memahami apa yang mereka baca, pun begitu mereka sedang mendengar ‘suara liyan’. Inilah definisi sastra yang saya sangat sukai: mendengarkan suara liyan. Kita tidak boleh lupa betapa berbahayanya ketika kita berhenti mendengarkan liyan ketika mereka menggugat kita! Kita bakal terjun bebas ke dalam swa-isolasi; kita bakal memasuki semacam ‘ketulian spiritual’, yang berdampak negatif ke dalam hubungan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan, terlepas dari sebanyak apapun pelajaran teologi dan psikologi yang telah kita terima.
- Pendekatan ini atas susastra, yang menjadikan kita sensitif atas misteri orang lain, mengajarkan kita untuk menyentuh hati mereka. Saya terpikir tentang permohonan yang disampaikan oleh Santo Paul VI dengan berani kepada para seniman dan pula para penulis pada 7 Mei 1964: “Kami membutuhkanmu. Pelayanan butuh kerjasamamu. Sepanjang yang kalian tahu, pelayanan kami adalah dakwah, dan memastikan dunia roh, dunia yang tak kasat, yang tak terkatakan dari Tuhan, dapat diakses dan dipahami, bahkan menggerakkan. Dan kalian adalah para ahli di bidang ini, bidang yang melukiskan dunia tak kasat lewat cara-cara yang mudah dipahami dan diakses”.14 Inilah poinnya: tugas orang beriman, dan para pendeta khususnya, adalah secara tepat ‘menyentuh’ hati orang lain, sehingga mereka membuka hatinya terhadap pesan-pesan Tuhan Yesus. Dalam tugas akbar ini, kontribusi yang ditawarkan sastra dan puisi punya nilai yang tidak terbanding.
- T.S. Eliot, seorang penyair yang puisi dan esainya mencerminkan keimanan kristianinya, punya tempat yang begitu khusus dalam sastra kiwari, yang secara perseptif menggambarkan krisis agama hari ini sebagai kelumpuhan emosional yang meluas.15 Jika kita mempercayai diagnosa berikut, masalah keimanan hari ini bukan semata-mata perkara lebih atau kurang beriman atas doktrin-doktrin tertentu. Alih-alih, ihwal ini adalah bukti ketidakmampuan masyarakat untuk secara mendalam tergerak di hadapan Tuhan, makhluk-makhlukNya, dan manusia lain. Di sinilah kita melihat pentingnya pengabdian dalam penyembuhan dan pengayaan dalam cara kita menanggapinya. Ketika pulang dari Perjalanan Apostolik saya ke Jepang, saya ditanyai soal pandangan saya mengenai apa yang bisa Barat pelajari dari Timur. Jawaban saya, “Saya pikir Dunia Barat kekurangan puisi.”16
‘Latihan Kearifan’
………………………………………………………………………… - Lalu, keuntungan apa yang diraih oleh para pendeta dari bersentuhan dengan susastra? Mengapa dirasa perlu untuk mempertimbangkan dan menggencarkan membaca novel-novel baik sebagai elemen penting dalam pendidikan (paideia) kependetaan? Mengapa penting bagi kita, dalam melatih kandidat pendeta, untuk memulihkan pandangan Karl Rahner yang menyatakan bahwa ada kedekatan rohani yang mendalam antara para pendeta dan penyair?17
- Mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mendengarkan apa yang teolog Jerman itu katakan.18 Bagi Rahner, sabda penyair penuh dengan nostalgia, mengingat, mereka seperti, “gerbang menuju yang tak terbatas, gerbang menuju yang tak terpahami. Mereka menyeru sesuatu tak bernama. Mereka menggapai apa yang tak tersentuh.” Puisi, “tidak menyerahkan ketakterbatasan dalam dirinya, tidak pula membawa dan mengandungnya.” Tugas-tugas seperti itu adalah tugas firman Tuhan dan, seperti apa yang Rahner kemudian katakan, “kata yang puitis menyerukan firman Tuhan.”19 Bagi umat Kristiani, Firman adalah Tuhan, dan seluruh diksi manusia mengandung jejak kerinduan intrinsik akan Tuhan, meniru apa yang menjadi Firman. Bisa dikatakan bahwa kata-kata yang benar puitis, secara analogis, merupakan bagian dari Firman Tuhan, sebagaimana jelas tertera dalam Surat kepada Orang Ibrani (lihat Ibrani 4:12-13).
- Mengingat hal ini, Karl Rahner mampu menarik paralel antara pendeta dan penyair: kata “dan hanya kata-kata yang dapat menebus apa-apa yang menjadi pemenjaraan pamungkas dari semua realitas yang tidak dapat dapat diungkapkan dalam kata: kebisuan referensi mereka atas Tuhan.”20
- Sastra kemudian, membuat kita lebih peka terhadap hubungan antara bentuk ekspresi dan makna. Sastra menawarkan latihan kearifan, mempertajam kemampuan para calon pendeta untuk memandang ke dalam dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Membaca kemudian menjadi ‘jalan’ yang menuntunnya kepada kebenaran keberadaan dirinya dan kesempatan untuk meraih kearifan rohani yang bakal dipenuhi dengan kecemasan dan bahkan krisis. Bahkan, banyak halaman susastra yang selaras dengan apa yang dibilang oleh Santo Ignatius sebagai ‘kemurungan’ rohani.
- Ignatius menjabarkannya sebagai berikut: “Saya menyebutnya kemurungan gelap dari jiwa, kebisingan roh, kecenderungan pada apa yang keji dan fana, kegaduhan yang terbit dari begitu banyak gangguan dan godaan yang menuntun pada angan atas iman, harapan, dan cinta. Jiwanya telah begitu malas, lembek, menyedihkan, dan jauh dari Pencipta dan Tuhannya.”21
- Kesulitan dan ujian yang kita rasakan saat membaca teks tertentu tidak melulu buruk atau nirguna. Ignatius sendiri telah mengamati bahwa dalam “mereka-mereka yang beralih dari buruk ke terpuruk,” sang roh baik bekerja dengan menantang kegaduhan, agitasi, dan ketidakpuasan.22 Ini tentu saja merupakan penerapan harfiah dari aturan Ignatian pertama tentang kearifan rohani, yang berurusan dengan mereka, “yang beranjak dari dosa daging satu ke yang lain.” Dalam orang-orang tersebut terdapat roh baik, dengan “menggunakan terang akal budi yang akan membangkitkan sengatan nurani dan memenuhinya dengan rasa bersalah,”23 dan melalui cara inilah yang akan menuntun mereka kepada kebaikan dan keindahan.
- Menjadi jelas kemudian, bahwa para pembaca tidak sekadar penadah dari pesan-pesan mendidik, namun juga seorang insan yang ditantang untuk terus maju di atas medan yang bergejolak di mana batas antara pertaubatan dan kebinasaan tidak selalu jelas dan tegas di kepala mereka. Membaca , sebagai tindak ‘pengarifan’, secara langsung melibatkan pembaca baik sebagai ‘subyek’ yang membaca dan sebagai ‘obyek’ dari apa yang dibaca. Dalam membaca novel atau karya puisi, pembaca benar-benar mengalami ‘pembacaan’ oleh kata-kata yang mereka baca.24 Para pembaca kemudian dapat membandingkan diri mereka dengan para pemain di lapangan: mereka bermain di pertandingan, namun pertandingan tersebut turut memainkan mereka, dalam arti mereka benar-benar terlibat dan fokus dalam tindak permainannya.25
Perhatian dan penyerapan
………………………………………………………………………… - Dalam mempertimbangkan isi, kita harusnya menyadari bahwa sastra laiknya ‘teleskop’, meminjam dari istilah Marcel Proust.26 Seperti itulah, sastra diarahkan kepada makhluk dan benda, dan mengizinkan kita untuk menyadari ‘jarak luas’ yang memisahkan totalitas pengalaman manusia dari persepsi kita atasnya. “Sastra dapat juga dibandingkan dengan foto kamar gelap, di mana gambar kehidupan dapat diproses untuk menampilkan kontur dan nuansanya. Inilah fungsi sastra: sastra membantu kita untuk ‘memperjelas’ gambar kehidupan,”27 untuk mendorong kita memahami maknanya, dan, dengan kata lain, mengalami kehidupan sebagaimana mestinya.
- Bagaimanapun, pandangan tipikal kita terhadap dunia cenderung ‘terteleskopkan’ dan disempitkan oleh tekanan mendesak sebab berbagai tujuan-tujuan praktis dan jangka pendek. Bahkan dalam komitmen kita terhadap kebaktian—liturgis, kepasturan, dan amal—dapat begitu diruncingkan pada perkara tujuan yang harus dicapai. Pun begitu, sebagaimana Yesus telah mengingatkan kita dalam parabel sang penabur, benih perlu jatuh di tanah yang digali agar matang berbuah di kemudian hari, tanpa tercekik oleh tanah berbatu atau onak duri (Matius 13:18-23). Selalu ada risiko bahwa perhatian yang berlebih terhadap efisiensi akan menumpulkan kearifan, melelmahkan sensitivitas, dan mengabaikan kerumitan. Kita benar-benar butuh mengimbangi godaan yang tak terhindarkan dari gaya hidup yang hingar-bingar nan tidak kritis dengan mundur, melamban, dan mengambil waktu untuk melihat serta mendengan. Hal ini dapat terjadi belaka jika seseorang memutuskan untuk mampir membaca buku.
- Kita perlu menggali cara-cara untuk memahami kenyataan yang lebih hangat, tidak melulu strategis dan ditujukan pada hasil, cara-cara yang mengizinkan kita untuk mengalami kemengadaan akbar nan tidak-terbatas. Nalar bersudut pandang, menghibur, dan membebaskan adalah markah dari sebuah pendekatan atas realitas yang menyadari di dalam sastra sebuah bentuk ungkapan yang terjunjung, walau tidak eksklusif. Susastra kemudian mengajari kita cara melihat dan memperhatikan, mempertimbangkan dan menjelajahi realitas para individu dan situasi-situasi sebagai sebuah misteri yang dipenuhi oleh makna berlimpah yang hanya dapat dipahami sebagian melalui kategori, skema penjelasan, dinamika linear dari sebab-akibat, cara, dan tujuan.
- Citra lain tentang peran susastra datang dari aktivitas jasad manusia, khususnya kegiatan pencernaan. Biarawan abad kesebelas bernama William of Saint-Thierry dan Yesuit abad ketujuhbelas bernama Jean-Joseph Surin menggunakan citra seekor sapi yang memamah—ruminatio—sebagai gambaran dari pembacaan kontemplatif. Surin merujuk kepada ‘lambung jiwa’, sementara Yesuit Michel De Certeau telah berbicara tentang ‘fisiologi pembacaan digestif’ yang otentik.28 Sastra membantu kita untuk merefleksikan makna dari keberadaan kita di dunia ini, untuk ‘mencerna’ dan mengasimilasinya, dan untuk menyingkap apa yang terletak di balik permukaan pengalaman kita. Susastra, dengan kata lain, bekerja untuk menafsirkan kehidupan, untuk mengarifi makna lebih dalamnya dan tegangan-tegangan pentingnya.29
Mengamati via mata orang lain
………………………………………………………………………… - Dalam medan penggunaan bahasa, membaca teks sastra menempatkan kita dalam posisi untuk ‘mengamati via mata orang lain’,30 sehingga kita menghirup nafas sudut pandang yang memperluas kemanusiaan kita. Kita mengembangkan empati imajinatif yang mengizinkan kita untuk mengenali bagaimana orang lain mengamati, mengalami, dan merespon kenyataan. Tanpa empati, tidak akan ada solidaritas, berbagi, kasih sayang, dan pengampunan. Dalam membaca kita menemukan bahwa perasaan kita bukanlah milik kita sendiri, mereka universal, dan orang paling papa sekalipun tidak akan merasa sendirian.
- Kebhinnekaan manusia yang mengagumkan, dan pluralitas diakronis serta sinkronis kebudayaan dan medan pembelajaran, dalam sastra menjelma sebuah bahasa yang mampu menghormati dan mengungkapkan semua keberagamannya. Secara bersamaan, mereka termaknai ke dalam tata simbolis yang menjadikannya bermakna bagi kita, tidak asing namun dirayakan bersama. Keunikan susastra terletak pada fakta bahwa sastra mengandung kekayaan pengalaman dengan tidak mengobyektifikasinya sebagaimana model deskriptif ilmu pengetahuan ataupun penghakiman kritisisme sastra, namun dengan mengungkapkan dan menafsirkan makna lebih dalamnya.
- Ketika kita membaca secarik kisah, berkat kekuatan deskriptif dari para penulis, setiap dari kita dapat melihat di depan kita tangisan anak gadis yang terlantar, seorang nenek lanjut usia yang menarik selimut cucunya yang tertidur, perjuangan seorang penjaga toko untuk sekadar bertahan hidup, rasa malu seseorang yang memanggul beban berat kritisisme, seorang bocah laki-laki yang berlindung di balik mimpi sebagai satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang keras dan jahannam. Semua cerita ini membangkitkan gema lirih dari pengalaman di dalam diri kita, kita menjadi lebih sensitif terhadap pengalaman orang lain. Kita melangkah keluar dari diri kita dan memasuki kehidupan mereka, kita bersimpati dengan perjuangan dan hasratnya, kita mengamati melalui mata mereka dan kemudian kita menjelma pendamping perjalanan mereka. Kita tertangkup pada kehidupan sang penjual buah, pelacur, anak yatim, istri seorang tukang bata, nenek tua yang masih percaya akan menemukan pangerannya. Kita dapat melakukan semua ini dengan empati dan terkadang dengan kelembutan dan pemahaman.
- Seperti yang ditulis oleh Jean Cocteau kepada Jacques Maritain: “Sastra itu mustahil. Kita harus keluar darinya. Tidak berguna untuk keluar melalui sastra’ hanya cinta dan iman yang mengizinkan kita untuk keluar dari diri kita sendiri.”31 Pun begitu, apakah kita bisa benar-benar keluar dari diri kita sendiri jika penderitaan dan kebahagiaan liyan tidak membara di dalam jiwa kita? Di sinilah, bagi kita umat Kristiani, saya pikir, tidak ada sesuatu apapun yang bersifat manusiawi yang asing bagi kita.
- Susastra tidak bersifat taksa; sastra tidak mencerabut nilai dari diri kita. Representasi simbolis dari kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebohongan, sebagaimana realitas dalam sastra mengambil bentuk sebagai individu dan peristiwa sejarah kolektif, tidak membebaskan kita dari penilaian moral namun mencegah kita dari penghakiman yang dangkal dan buta. Sebagaimana Yesus sabdakan, “Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?” (Matius 7:3).
- Ketika membaca tentang kekerasan, kebanalan, dan kerapuhan pada liyan, kita punya kesempatan untuk merefleksikan pengalaman kita sendiri terhadap realitas berikut. Dengan membuka diri terhadap pandangan yang lebih luas atas kemegahan dan penderitaan pengalaman manusia kepada para pembaca, susastra mengajarkan kita kesabaran dalam upaya memahami orang lain, kerendah hatian dalam mendekati situasi rumit, kelembutan dalam penghakiman kita atas individu, serta kepekaan terhadap kondisi manusiawi kita. Penghakiman tentu saja diperlukan, namun kita musti tidak boleh lupa tentang betapa sempit batasan penghakiman. Penghakiman hendaknya tidak boleh dijatuhkan dalam hukuman mati, menyingkirkan orang, atau menekan kemanusiaan kita hanya demi kepatuhan tanpa jiwa atas hukum.
- Kearifan yang lahir dari sastra menanamkan perspektif yang lebih luas, pemahaman atas batasan, kemampuan untuk menghargai pengalaman di atas kecerdasan dan penalaran kritis, serta memeluk kemiskinan yang membawa kelimpahan luar biasa kepada para pembaca. Dengan mengakui kesia-siaan dan mungkin malah kemustahilan dalam mereduksi misteri dunia dan kemanusiaan ke dalam pengkutuban dualistis benar-salah baik-jahat, para pembaca dapat menerima tanggung jawab dalam melakukan penghakiman, bukan sebagai cara untuk mendominasi, melainkan sebagai dorongan untuk mendengar lebih banyak. Di saat yang bersamaan, pula kesiapan untuk mengambil bagian dalam kekayaan sejarah yang luar biasa yang disebabkan oleh Roh, yang diberikan jua sebagai berkat, seperangkat peristiwa yang tidak dapat diduga dan dipahami yang tidak bergantung pada aktivitas manusiawi, namun mendefinisikan ulang kemanusiaan kita dalam kerangka harapan atas keselamatan.
Daya rohani sastra
………………………………………………………………………… - Saya percaya bahwa bersama refleksi singkat ini, saya telah menekankan peran sastra dalam pembinaan hati dan nalar para pendeta dan calon pendeta. Sastra dapat merangsang ungkapan bebas nan sederhana dari akal yang kita gunakan, pengakuan atas berbagai bahasa manusia yang bermanfaat, peluasan kepekaan manusiawi kita, dan akhirnya, keterbukaan rohani yang akbar dalam mendengar Wahyu yang berbicara lewat banyak suara.
- Sastra menolong para pembaca untuk meruntuhkan berhala bahasa konvensional yang swarujuk, merasa cukup padahal tipu-tipu, dan statis sehingga seringnya malah beresiko mencemari diskursus gerejawi, berakhir memenjarakan kebebasan Firman. Kata-kata dalam susastra adalah kata-kata yang menggerakkan, membebaskan, dan memurnikan bahasa. Pamungkasnya, susastra mengangkat kata ke wilayah yang jauh lebih ekspresif dan ekspansif. Susastra pula yang mengetuk kata-kata manusiawi untuk menyambut Firman yang telah hadir di lidah manusia, bukan ketika sastra melihat dirinya sendiri sebagai pengetahuan yang lengkap, definitif, dan utuh, melainkan ketika sastra menjelma pendengar dan penanti Ia yang datang untuk menjadikan segala sesuatu baru (lihat Wahyu 21:5).
- Akhirnya, daya rohani dalam sastra mengembalikan kita kepada tugas utama yang dipercayakan oleh Tuhan kepada warga manusia: tugas untuk ‘menamai’ makhluk dan benda lain (lihat Kejadian 2:19-20). Misi sebagai pengurus ciptaan, ditugaskan oleh Tuhan kepada Adam, pertama-tama menuntut pengakuan atas martabatnya sendiri dan makna keberadaan makhluk lain. Para imam juga dipercayakan dengan tugas utama ini untuk “memberi nama”, menyemat makna, menjelma perangkat persekutuan antara ciptaan dan Firman yang menjadi daging serta kuasanya untuk menerangi setiap matra kondisi manusiawi kita.
- Keakraban antara pendeta dan penyair kemudian bersinar dalam persatuan sakramental yang misterius dan tak terpisahkan antara Firman ilahi dan kata-kata manusiawi kita, melahirkan pelayanan yang lahir dari sikap mendengarkan dan belas kasih, karisma yang menjadi tanggung jawab, visi tentang kebenaran dan kebaikan yang menyingkapkan dirinya sebagai keindahan. Bagaimana mungkin kita tidak merenungkan kata-kata yang ditinggalkan oleh penyair Paul Celan: “Mereka yang benar-benar belajar melihat, akan mendekati apa yang tak terlihat”.32
Disampaikan di Roma, dalam Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, pada 17 Juli tahun 2024, yang keduabelas dari Kepausan saya.
FRANCIS
- R. LATOURELLE, Literature, in R. LATOURELLE & R. FISICHELLA, Dictionary of
Fundamental Theology, New York 2000, 604. ↩︎ - Lihat A. SPADARO, J. M. Bergoglio, il ‘maestrillo’ creativo. Intervista all’alunno Jorge Milia, dalam La Civiltà Cattolica 2014 I 523-534. ↩︎
- SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, 62. ↩︎
- K. Rahner, Il futuro del libro religioso, dalam Nuovi saggi II, Roma 1968, 647. ↩︎
- Lihat Apostolic Exhortation, Evangelii Gaudium, 117. ↩︎
- A. SPADARO, Svolta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea, Milan, Vita e Pensiero, 101. ↩︎
- R. LATOURELLE, Literature, in R. LATOURELLE & R. FISICHELLA, Dictionary of
Fundamental Theology, New York 2000, 603. ↩︎ - SAINT JOHN PAUL II, Letter to Artists, 4 April 1999, 6. ↩︎
- Apostolic Exhortation, Evangelii Gaudium, 89. ↩︎
- SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, 22. ↩︎
- M. PROUST, À la recherche du temps perdu – Du côté de chez Swann, B. Grasset, Paris 1914, 104-105. ↩︎
- C.S. LEWIS, An Experiment in Criticism, 89. ↩︎
- Lihat J.L. BORGES, Borges, Oral, Buenos Aires 1979, 22. ↩︎
- SAINT PAUL VI, Homily, Mass with Artists, Sistine Chapel, 7 May 1964. ↩︎
- Lihat T.S. Eliot, The Idea of a Christian Society, London 1946, 30. ↩︎
- Press Conference on the Return Flight to Rome, Perjalanan Kerasulan ke Thailand dan Jepang, 26 November 2019. ↩︎
- Lihat A. SPADARO, La grazia della parola. Karl Rahner e la poesia, Milan, Jaca Book, 2006. ↩︎
- Lihat K. Rahner, Theological Investigations, Vol. III, London 1967, 294-317. ↩︎
- Ibid. 316-317. ↩︎
- Ibid. 302. ↩︎
- SAINT IGNATIUS LOYOLA, Spiritual Exercises, n. 317. ↩︎
- Lihat ibid., n. 335. ↩︎
- Ibid., n. 314 ↩︎
- Lihat K. Rahner, Theological Investigations, Vol. III, London 1967, 299. ↩︎
- Lihat A SPADARO, La pagina che illumina. Scrittura creativa come esercizio spirituale, Milan, Ares, 2023, 46-47. ↩︎
- M. PROUST, À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé, Vol. III, Paris 1954, 1041. ↩︎
- A SPADARO, La pagina che illumina. Scrittura creativa come esercizio spirituale, Milan, Ares, 2023, 14. ↩︎
- M. DE CERTEAU, Il parlare angelico. Figure per una poetica della lingua (Secoli XVI e XVII), Firenze 1989, 139 ff. ↩︎
- A SPADARO, La pagina che illumina. Scrittura creativa come esercizio spirituale, Milan, Ares, 2023, 16. ↩︎
- Lihat C.S. LEWIS, An Experiment in Criticism. ↩︎
- J. COCTEAU – J. MARITAIN, Dialogo sulla fede, Firenze, Passigli, 1988, 56; Lihat A
SPADARO, La pagina che illumina. Scrittura creativa come esercizio spirituale, Milan, Ares, 2023, 11-12. ↩︎ - P. CELAN, Microliti, Milan 2020, 101. ↩︎
Hak Cipta © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana


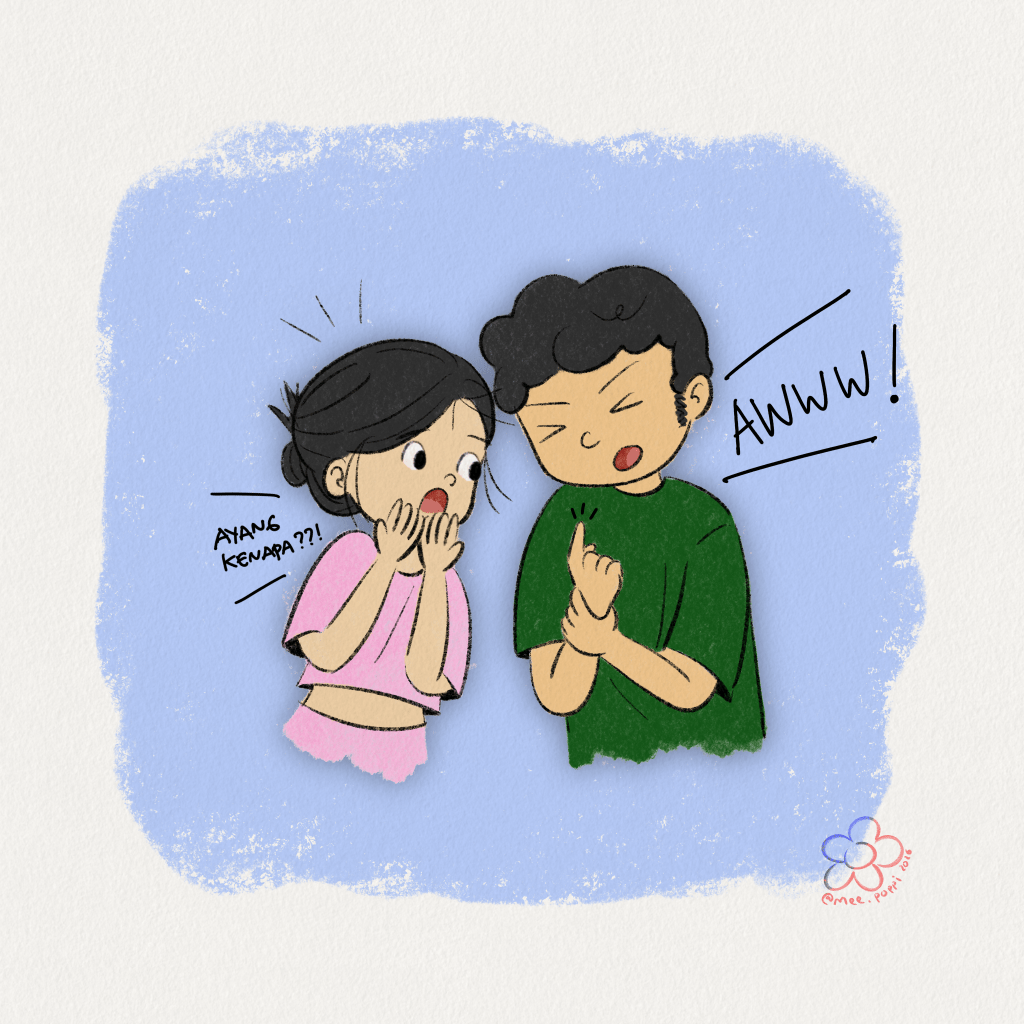


Leave a comment