Pertama kali diterbitkan oleh Tilik Sarira. Mengingat situs web mereka sudah tidak lagi aktif, esai berikut kuterbitkan kembali di rumah ini!
Saya paling benci dengan lomba seni tanpa catatan dari para juri. Karya dimenangkan serta-merta, tanpa ada pembelaan lebih lanjut mengapa karya tersebut bisa menang. Tidak muluk-muluk, saya sendiri juga sudah senang jika diberi satu paragraf. Juri sudah bekerja, maka juri perlu mempertanggungjawabkannya. Masa setiap seniman ditanya proses kreatifnya—walau seringkali tidak perlu—, tapi juri tidak boleh diintip dapurnya?
Maka, saya suka sekali jika Dewan Kesenian Jakarta mengadakan lomba. Tahun 2021, bahkan para dewan juri memutuskan untuk mengumumkan tiga karya terbaik sayembara puisinya tanpa juara pertama! Keberanian sikap ini kemudian didukung oleh pertanggungjawaban yang mudah sekali diakses.
Nah, bakda mengutarakan kesukaan dan keengganan saya atas kecenderungan medan seni tersebut—sebagai sebuah sikap mula, saya angan menanggapi tulisan Rudi Agus Hartanto bertajuk Di Hadapan Perlombaan Seni. Saya punya kehendak menulis keping ini sejak lama—sejak tulisan ini saya baca pertama kali pada kuartal keempat 2023, namun apalah, hidup melanda.
Menjawab Pertanyaan, “Apakah Seni Bisa Dilombakan?”
Jawaban pendeknya, “Bisa!”
Jawaban sedikit panjangnya, “Bisa banget!” Namun, apalah guna pertanyaan sebagai pondasi proyek filsafat—dalam kasus ini, estetika, jika jawabannya malah menganulir polemik? Maka, izinkan saya turut urun pandangan.
Ah, sebelumnya: mengapa pertanyaan tersebut kemudian menjelma proyek (eksplorasi) estetika?1 Karena pertanyaan tersebut berkaitan dengan salah satu pilar filsafat yang disebut aksiologi.2 Aksiologi berkutat pada masalah nilai (baik-buruk, perlu-tidak perlu)—yang secara harfiah, inheren dalam perlombaan (karena juri menilai). Perihal aksiologi ini juga bisa disematkan pada persoalan guna: untuk mengkaji perlunya kompetisi seni di realitas sehari-hari, dan nilai apa yang bisa kita ambil dari fenomena tersebut.
Baik, mari kembali bergelut dengan persoalan lebih lanjut setelah pertanyaan di atas dijawab kemudian menjelma, “Bagaimana bisa seni dilombakan? Mengapa bisa dilombakan?”
“Bagaimana Bisa Seni Dilombakan?”
Mari tengok kegelisahan Rudi di paragraf pengantarnya, “…lahir anggapan kemenangan tersebut telah menandai keterancaman dunia seni.” (paragraf 1), yang membicarakan tentang gubahan Midjourney (aplikasi manipulasi gambar oleh kecerdasan buatan) yang memenangkan sayembara tahunan seni rupa helatan Colorado State Fair pada tahun 2022 silam. ‘Keterancaman’ di sini sebenarnya agak keliru pertimbangan dan goyah sikap. Sampai saat ini, hasil gubahan tersebut tidak dapat memperoleh hak cipta, berbeda dengan hasil sketsa tangan di buku sketsa yang sudah terlindungi sejak digoreskan.
Pembelaan terhadap kemenangan Théâtre D’opéra Spatial tentu ada saja, beberapa bahkan menyamakannya dengan manipulasi foto terbatas serta penggunaan kamera digital pada kompetisi fotografi. Toh, di kompetisi lain, diskualifikasi—sejak era Photoshop—sudah sering terjadi. Anggaplah itu bagian dari polemik. Kegelisahan Rudi agak keliru karena, ‘keterancaman’ tidak terletak pada kecerdasan buatan yang berhasil ‘menaklukkan’ seni: melainkan, pada nihilnya pembelaan para dewan juri yang bersikukuh untuk tetap memenangkan Théâtre D’opéra Spatial. ‘Keterancaman’ juga terletak pada minimnya sikap medan seni atas perkembangan kecerdasan buatan dan longgarnya regulasi atas pemelajaran mesin (machine learning) pada umumnya. Inilah mula kegoyahan sikap dalam refleksi Rudi.
Lalu, bagaimana seni bisa dilombakan? Karena baiknya penalaran ini dirunut melalui kesejarahannya, maka pertanyaan perlu dikembangkan: bagaimana awal mula seni bisa dilombakan?
Kebaptisan Firenze sudah bercokol seabad dan tertatah pada identitas Firenze ketika gilda pedagang wol, Arte del Calimala, diserahi tanggung jawab untuk merawat dan memperindahnya. Proyek dekorasi ini bermula di abad kedua belas, ketika Calimala menghelat kompetisi seni untuk sepasang daun pintu baru. Kompetisi ini bertemakan kisah Ibrahim yang mengorbankan Ishak dalam mitologi Kristen. Syarat pun diberlakukan: dijatahi bahan perunggu pada jumlah tertentu dan panel daun harus berbentuk quatrefoil. Dewan jurinya berjumlah banyak sekali, dengan perbandingan terhadap peserta 34:7. Di akhir kompetisi, seluruh peserta yang juga seniman tereliminasi, kecuali Lorenzo Ghiberti dan Filippo Brunelleschi. Namun, karya pemenang yang dipilih hanya satu. Ghiberti akhirnya memenangkan kompetisi tersebut dan membawa pulang hadiah sebanyak 4.000 florin, atau setara dengan 8,4 milyar rupiah hari ini.3
Hasil kompetisi sembilan abad silam tersebut, sampai sekarang masih bisa dinikmati publik sebagai bagian dari pendidikan seni. Inilah salah satu ibrah yang bisa diambil dari muasal sayembara seni. Ibrah lainnya adalah: syarat memang harus ketat, dewan juri harus bertanggung jawab untuk mewakili—entah publik atau diri sendiri, dan hasilnya adalah untuk pendidikan seni. Inilah syarat dasar lomba seni untuk diadakan, sejak kompetisi belum ‘dimurnikan’ dalam bentuk ideologi bernama kapitalisme.
Perihal pendidikan seni kemudian tertaut dengan perihal wacana seni. Wacana seni sendiri, dalam pergulatannya, semakin menjauhi wacana besar, universal, dan tunggal yang dibawa oleh modernisme. Modernisme sebagai proyek filsafat sudah bangkrut.4 Maka, wacana seni dengan sendirinya kemudian semakin subyektif—dalam penalaran berorientasi subyek atau berangkat dari subyek tunggal. Inilah yang diperlukan dalam penilaian dalam lomba seni. Rudi menunjukkan bahwa, “…latar belakang aliran seni yang digeluti para juri juga tidak dapat ditanggalkan sepenuhnya,” (paragraf 3). Yang ditunjukkan Rudi sudah benar, namun implikasi negatif yang menjadi gagasan pokok paragraf tersebut agaknya keliru. Latar belakang para dewan juri, justru jangan ditanggalkan demi pendidikan seni.
Kemudian, pertanyaan terkembang membayangi, “Bagaimana bisa seni dilombakan dengan ekosistem yang seperti ini? Dengan lembaga seperti ini?” Rudi sudah lebih gamblang menuturkan masalah-masalahnya, mulai dari kolusi, upah juri yang lebih kecil dari pemenang, hingga pendanaan kreatif untuk seniman. Semua masalah yang dikemukakan oleh Rudi, adalah masalah konteks medan seni dalam merawat lembaga serta wacana kesenian di tengah ekosistem seni yang monolitik. Maksudnya, medan seni masih dibayangi oleh cara kerja korporatisme dan hubungan berbasis patron-klien yang opresif. Sehingga, ruang alternatif hanya punya wilayah gerak yang tidak banyak. Kesejahteraan pekerja seni kemudian menjadi agenda yang bersilang tumpang dengan moralitas5: seni tidak pernah dibiarkan untuk membicarakan dirinya sendiri, kecuali dengan membicarakan sponsornya. Seni sebagai kompas moral, kemudian dibenturkan dengan laku pemilik dana, yang notabene, lepas moral.6 Masalah ini kemudian juga menimpa lomba seni, sehingga Rudi pun merasa, “perlu didedah peranan lomba seni dalam menghadirkan dampak kepada ekosistem kesenian,” (paragraf 6). Saya tentu saja sangat sepakat!
“Mengapa Seni Bisa Dilombakan?”
Setelah berpanjang penelusuran, tiba saatnya untuk merenungkan hakikat lomba seni. Seni bisa dilombakan karena upaya manusiawi untuk mencari batas. Sebagaimana raga yang diolah para atlet dan dikompetisikan pada olimpiade, rasa yang diolah para seniman kemudian dilombakan untuk mencari, “Seberapa puncak kiranya manusia bisa berkarya?”
Maka, Rudi pun menekankan, “…pertanggungjawaban keputusan juga berkedudukan vital di mana publik yang hendak mengajukan perspektifnya memiliki argumentasi kuat,” (paragraf 11) dan saya tidak bisa lebih sepakat lagi. Lomba, diadakan oleh siapa pun, adalah milik publik jua. Publik bisa menuntut jika sayembara dirasa cemar—semakin buruk dengan nihil pertanggungjawaban, apalagi jika, “…yang acapkali ditemukan hanyalah pemeringkatan,” (paragraf 12).
Ketika akhirnya memandang lomba, baik dari luar (sebagai pemirsa dan peserta) maupun dari dalam (sebagai panitia dan dewan juri), menyadari relasi kuasa kelas dalam pembentukan keputusan—dan pamungkasnya selera pemenang adalah sama pentingnya dengan menyadari subyektivitasnya sendiri. Penting pula untuk memahami bahwa setiap lomba, sejak dihelat, adalah medan polemik bagi keberlangsungan wacana seni. Tujuan-tujuan sampiran seperti unjuk kompetensi, pengarsipan, urgensi tema, keragaman daya kritis gagasan, eksperimentasi, komersialisasi, serta prestise adalah pertimbangan lain lagi. Lebih bagus jika bisa dimaklumkan ke dalam pertanggungjawaban. Tidak pun, tidak menutup kanal untuk mengajukan keberatan-keberatan di wilayah tersebut. Agar pertanggungjawaban dan polemik sebagai responnya, “…memiliki jangkauan keterbacaan pengaruh terhadap penciptaan, pengkajian, dan tuntutan nilai kebaruan,” (paragraf 11).
Saya sepakat dengan Rudi yang menyatakan hakikat perlombaan seni yang, “…hendaknya dilihat sebagai ruang mencari tahu atau amatan ruang—zaman,” (paragraf 21). Namun, “Mitigasi terhadap risiko subyektivitas…” (ibid) sebagai argumen kemudian menjadi salah kaprah. Penilaian selalu bersifat subyektif. Justru, subyektivitas inilah yang kemudian harus dipertanggungjawabkan dengan ketat. Bagaimana caranya? Caranya dengan meletakkan keruangan lomba dalam medan seni dan wilayah wacana seni yang publik. Mawas atas hal-hal yang sudah dinalar di tulisan ini adalah salah satunya.
Bersenang-senang pun merupakan sikap subyektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa salahnya menghelat sayembara seni untuk, “…mengejar gayeng-gayengan saja,” (paragraf 21) kalau memang bisa membela maksudnya?
DI Hadapan Di Hadapan Perlombaan Seni
Memang, polemik di suatu medan kebudayaan selalu mencoba mencari jalan keluar yang jamak. Namun, argumen yang berusaha mengakomodir beragam sikap justru menunjukkan ketidakajegan. Alih-alih sintesis, yang didapat malah idiosinkrasi. Di Hadapan Perlombaan Seni merupakan refleksi yang masih berlaku sebagai moderator, alih-alih sudah bersikap sendiri. Ibarat menuding papan penunjuk jalan, tanpa menjabarkan lebih jauh apa yang kelak dihadapi pada jalan-jalan tersebut. Ironisnya, secara argumentatif, malah sama tidak transparannya dengan para dewan juri yang menjadi samsak kritik di seputar sayembara seni. Pun bertindak sebagai moderator, punya keajegan sikap itu tetap penting. Meluruhkan subyektivitas adalah langkah pemula belaka.
“Jadi, Apakah Seni Bisa Dilombakan?”
Sudah saya bilang, “Bisa banget!”*
*syarat dan ketentuan berlaku
- Suryajaya, Martin. 2016. Sejarah Estetika. Penerbit Gang Kabel ↩︎
- Craig, Edward. 2002. Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford University Press ↩︎
- Learning from Art History: Art Competition dipublikasikan oleh AGI Fine Art pada 19 Juni 2018 ↩︎
- Griffin, Roger. 2007. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. Palgrave Macmillan ↩︎
- Foster, Hal. 2015. Bad New Days: Art, Criticism, Emergency. Verso Books ↩︎
- The Dark World of Art Money Laundering dipublikasikan oleh Financial Crime Academy pada 23 Februari 2024 ↩︎


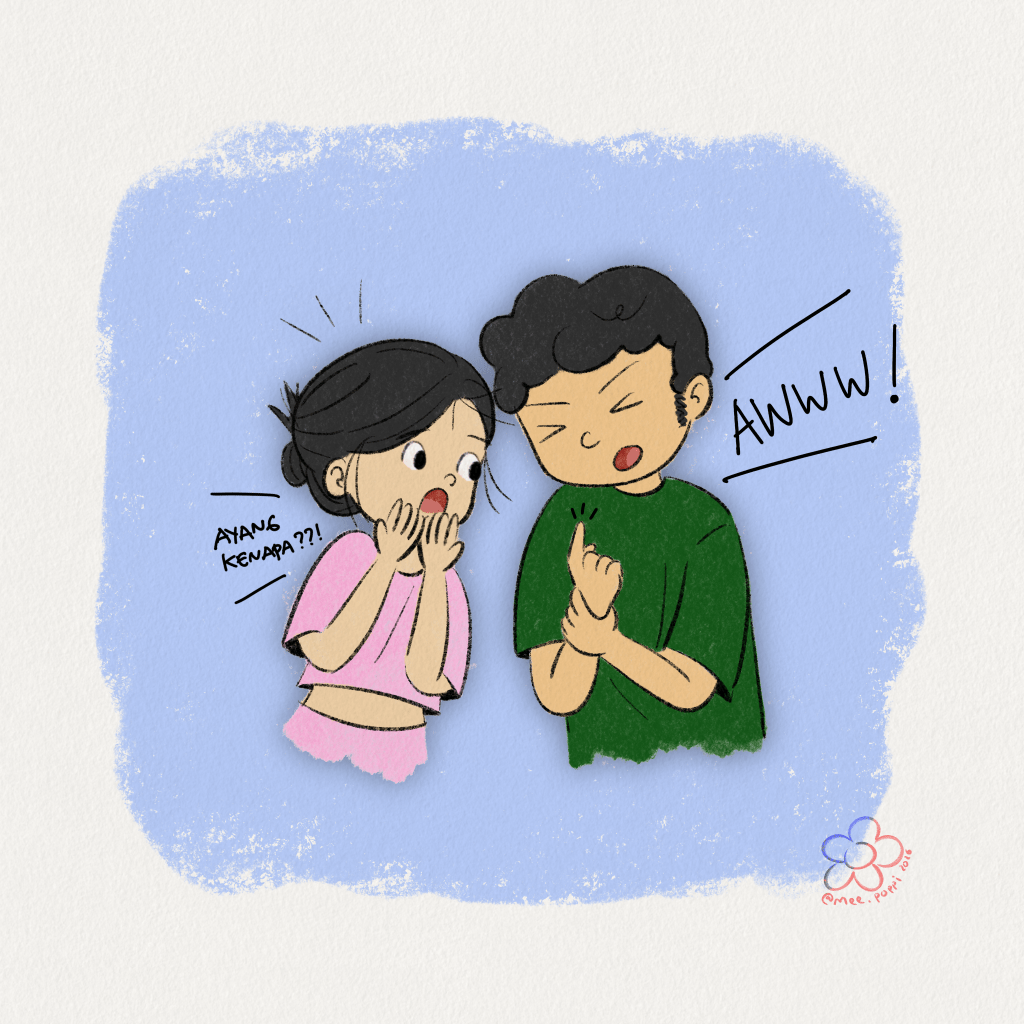


Leave a comment